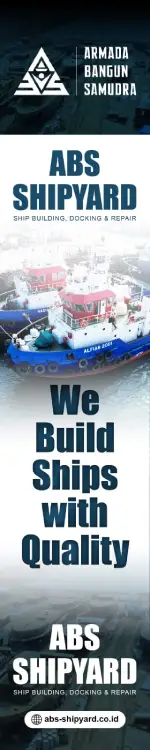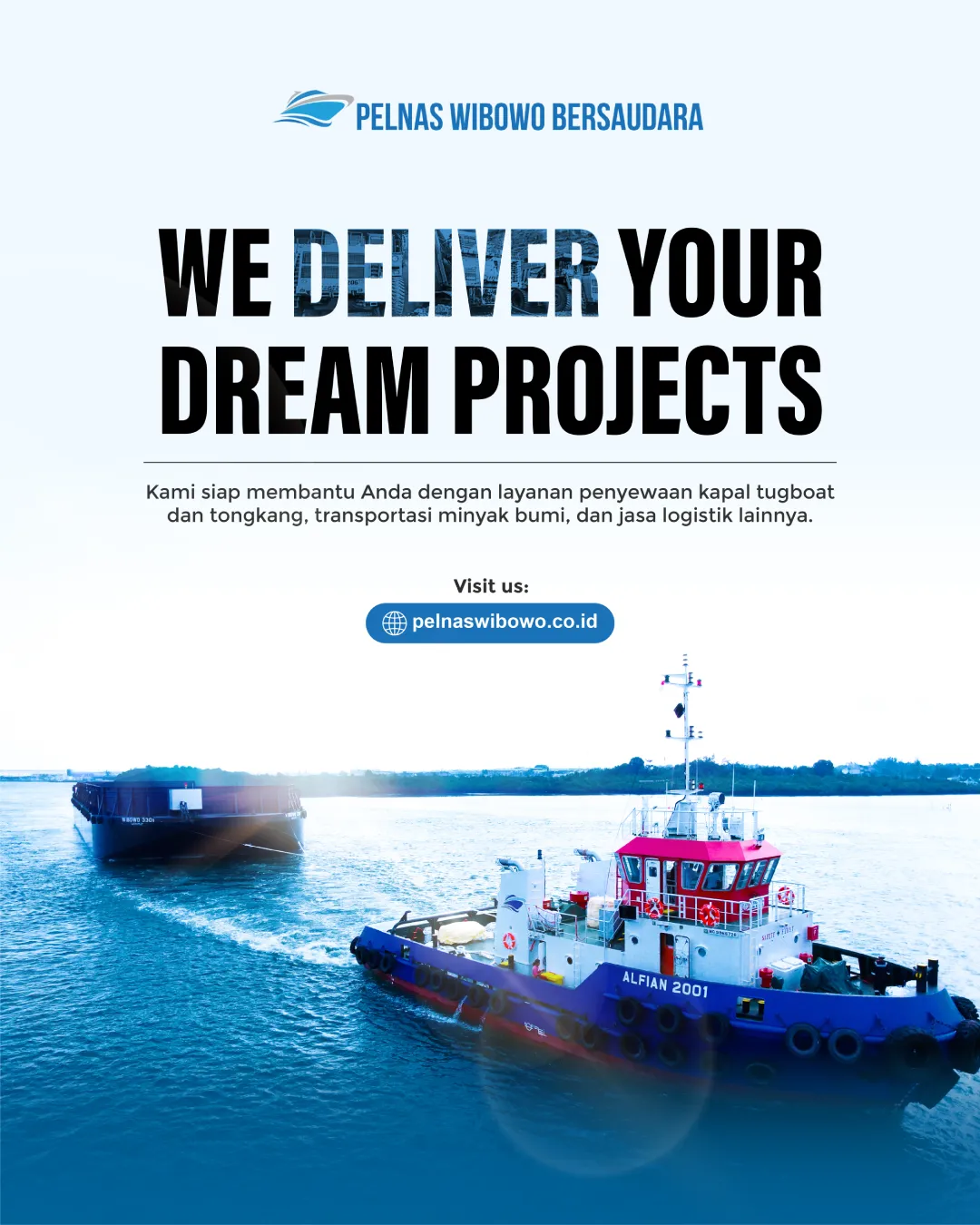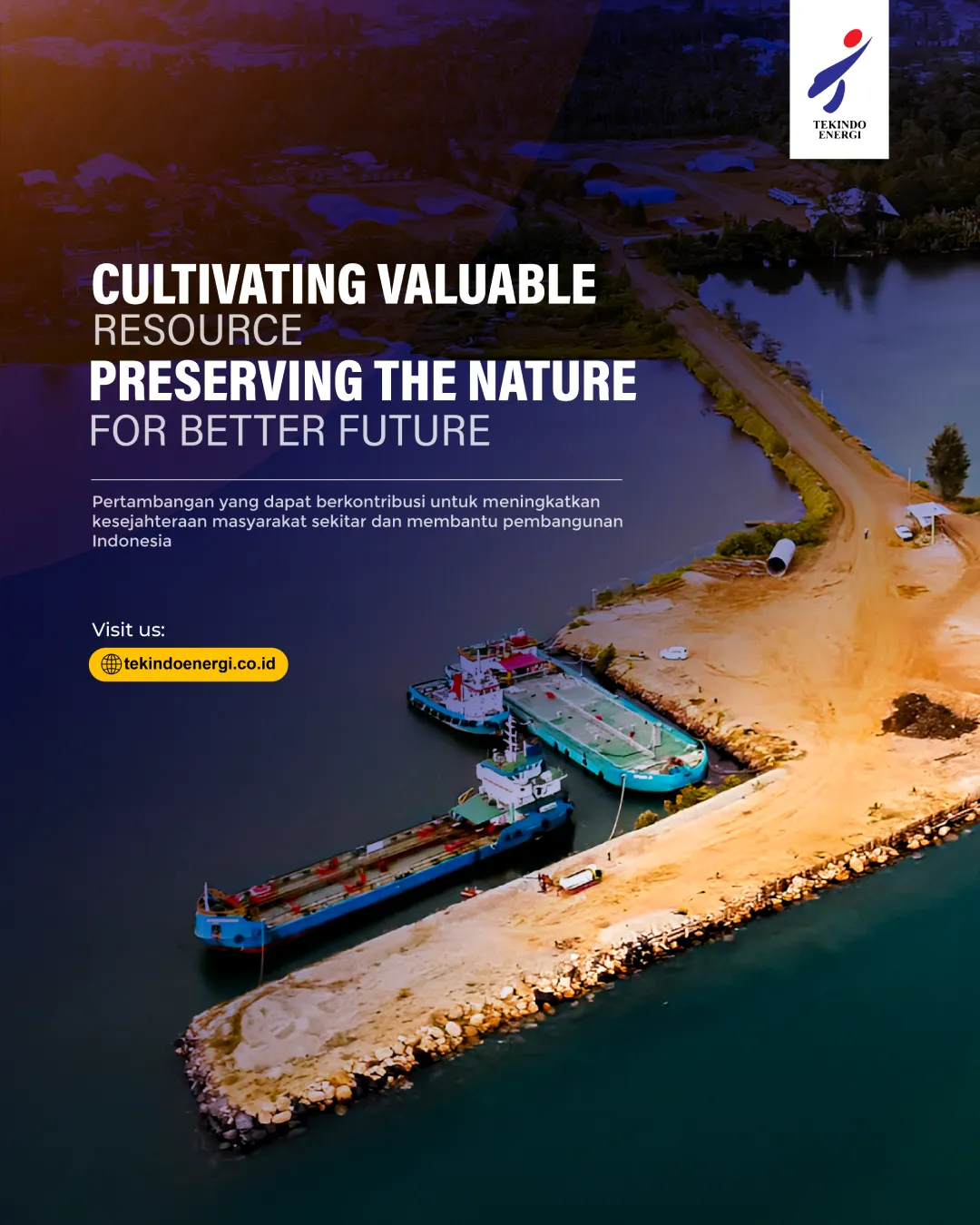BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Sajen bukan sekadar piring berisi bunga tujuh rupa, pisang, atau air putih. Bukan pula sekadar dupa yang mengepul dengan aroma khas. Lebih dari itu, sajen adalah cermin kebijaksanaan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sayangnya, dalam kehidupan masyarakat modern, makna sajen kerap disalahpahami—dikira mistis, bahkan dianggap menyalahi ajaran agama.
Namun di sejumlah daerah di Jawa Barat dan Jawa Timur, makna sajen tetap dijaga dan dimaknai sebagai bentuk syukur serta penghormatan kepada leluhur. Penelitian yang dilakukan oleh Yusup (2019) di Kampung Cipicung Girang, Kota Bandung, membuktikan bahwa praktik sajen bukanlah ritual gaib, melainkan bagian dari sistem nilai hidup masyarakat. Sajen menjadi cara masyarakat menyampaikan rasa terima kasih kepada Sang Pencipta atas berkah yang telah diterima.
Di kampung tersebut, sajen juga mengandung unsur pendidikan sosial. Sajen menjadi sarana menanamkan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, kebersamaan, dan pengendalian diri. Dalam setiap prosesi, penyusunan sajen tidak dilakukan sendiri, melainkan hasil kerja bersama warga. Setiap elemen yang digunakan memiliki makna. Misalnya, air putih melambangkan kejernihan hati dan niat yang tulus, sedangkan buah-buahan seperti pisang menjadi lambang kehidupan dan kelestarian.
Baca Juga:
Penampilan Tari Tradisional di Desa Sukasari Sambut Akhmad Marjuki
Mengenal Usik Sanyiru: Aksi Silat Tradisional di Atas Nyiru yang Tetap Lestari
Tak hanya di Cipicung, pemaknaan sajen juga hidup di Desa Kawedusan, Kabupaten Kediri. Dalam disertasinya, Yeni Nofita (2024) meneliti praktik sajen dalam ritual Sesaji Ki Ageng Boto Putih. Hasilnya, ditemukan bahwa masyarakat setempat memaknai sajen sebagai simbol penghormatan terhadap leluhur dan media untuk menjaga harmoni antarwarga.
Dalam setiap upacara, sajen disusun secara sistematis dan penuh kehati-hatian. Tak ada unsur kebetulan. Semua bahan yang digunakan dipilih berdasarkan makna filosofis. Seperti bunga sebagai perlambang keikhlasan, makanan khas desa sebagai bentuk pelestarian identitas lokal, dan dupa sebagai simbol penghubung antara dunia nyata dan alam gaib.
Sajen juga berperan sebagai jembatan antar generasi. Anak-anak yang dilibatkan dalam proses penyusunan sajen diajarkan filosofi di balik setiap bahan yang dipakai. Dengan begitu, nilai-nilai kearifan lokal tidak hanya berhenti pada tataran simbolik, tapi juga mengalir dalam laku hidup sehari-hari.
Makna sajen bahkan merambah ke ranah seni pertunjukan. Penelitian Karami yang mengangkat praktik sajen dalam kesenian kuda lumping di Sumedang menjelaskan bahwa setiap pertunjukan tradisional tak lepas dari keberadaan sajen sebagai bagian dari tata cara yang sakral. Sajen menjadi bentuk penghormatan terhadap roh leluhur, sekaligus sarana untuk menciptakan keseimbangan energi dalam ruang pertunjukan.
Dalam kesenian tersebut, sajen tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi juga sebagai elemen pengaman spiritual bagi para pemain dan penonton. Ayam panggang, kemenyan, hingga tumpeng kecil yang disajikan bukan untuk dipuja, tapi sebagai media pelindung dan pengingat bahwa manusia hidup berdampingan dengan alam dan kekuatan di luar logika.
Satu benang merah yang bisa ditarik dari berbagai daerah tersebut adalah bahwa sajen tak pernah berdiri sendiri. Ia hadir sebagai bagian dari sistem sosial yang utuh—di mana manusia, alam, dan leluhur saling terhubung dalam harmoni. Sajen bukan sekadar benda mati, melainkan medium komunikasi spiritual dan sosial yang merawat keseimbangan hidup.
Melalui berbagai praktik ini, terlihat bahwa sajen masih hidup. Ia bukan simbol masa lalu yang usang, melainkan penanda bahwa masyarakat masih punya akar. Dan seperti yang diyakini masyarakat Cipicung, Sumedang, hingga Kediri—selama sajen masih dipahami dengan niat baik, maka ia akan terus menjadi penuntun dalam menjaga nilai-nilai kehidupan.
Penulis:
Daniel Oktorio Saragih
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia (UNIBI)