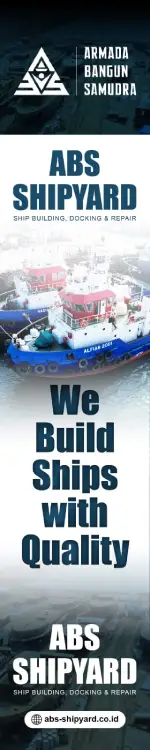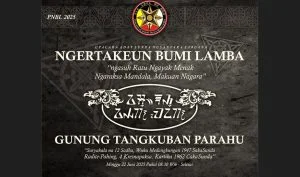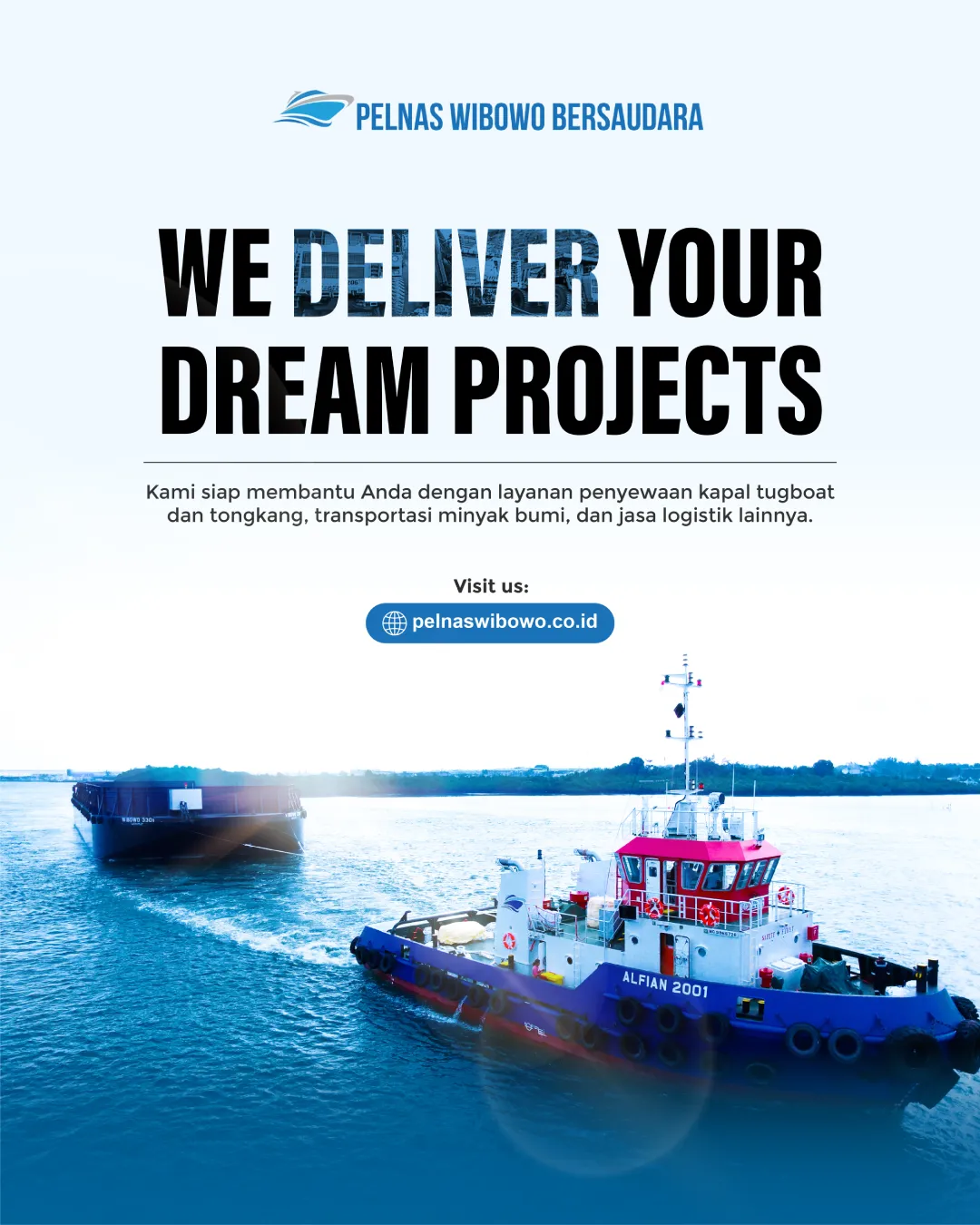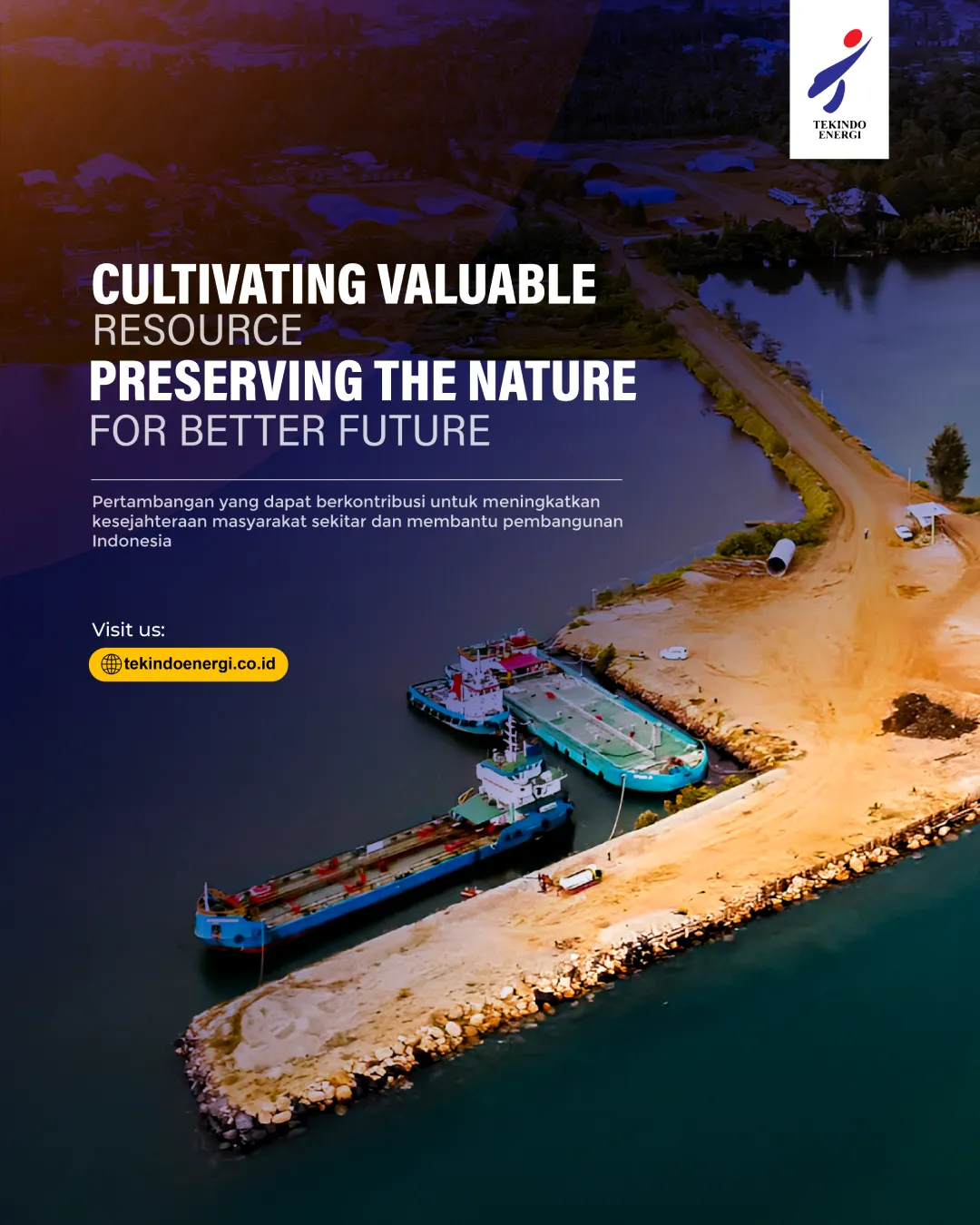BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Permainan tradisional adu muncang mungkin kini lebih dikenal sebagai hiburan anak-anak kampung di masa lalu. Namun siapa sangka, permainan yang tampak sederhana ini menyimpan sejarah panjang yang menarik, bahkan pernah menjadi kesenangan kalangan bangsawan di masa kerajaan.
Adu muncang adalah permainan yang menggunakan biji muncang, yakni biji dari pohon kemiri rambat (Aleurites moluccanus). Biji tersebut terkenal sangat keras, sehingga cocok untuk dijadikan alat adu dalam permainan. Cara memainkannya adalah dengan membenturkan dua biji muncang secara bergantian. Biji yang retak, pecah, atau terpental keluar dari arena dinyatakan kalah. Namun lebih dari itu, permainan ini sebenarnya mencerminkan kecerdikan, strategi, dan ketahanan—nilai-nilai yang secara tak langsung diwariskan melalui budaya bermain di masyarakat Sunda.
Masyarakat agraris di wilayah Tatar Sunda sejak lama telah akrab dengan muncang. Pohonnya mudah ditemukan di hutan atau kebun, dan bijinya kerap digunakan untuk bahan obat atau alat permainan. Seiring waktu, muncang menjadi bagian tak terpisahkan dari masa kecil banyak generasi. Namun di balik keceriaan anak-anak yang memainkannya, muncang ternyata memiliki catatan sejarah yang jauh lebih dalam.
Jejak sejarah adu muncang konon pernah masuk ke dalam lingkaran istana. Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa permainan ini pernah menjadi hiburan para bangsawan di zaman Kerajaan Sumedang Larang, bahkan sampai masa Kasultanan Cirebon dan Mataram. Tidak hanya dimainkan oleh rakyat jelata, muncang rupanya juga menarik perhatian para raja dan bangsawan sebagai permainan adu kekuatan sekaligus kecerdikan.
Pada masa itu, muncang diperlakukan hampir seperti benda prestise. Ada yang direndam dalam minyak khusus, dipilih dari biji terbaik, hingga diberi pelat logam kecil untuk memperkuat struktur luarnya. Beberapa bangsawan bahkan memerintahkan abdi dalem untuk mencari muncang terbaik dari hutan yang jauh, demi mendapatkan “jagoan” yang tak terkalahkan. Semakin sering muncang tersebut menang, semakin tinggi pula nilainya.
Dalam beberapa catatan lokal, disebutkan bahwa di lingkungan istana, pertandingan adu muncang bisa berlangsung dengan penuh gengsi. Tidak sedikit yang menjadikan kemenangan sebagai simbol kehebatan, bahkan sebagai taruhan harga diri. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun adalah tentang seorang bangsawan yang sangat mencintai muncangnya hingga menetapkan hukuman aneh: bila muncangnya kalah, kuda miliknya harus dikorbankan.
Leher kuda dipenggal sebagai bentuk “penebusan” kekalahan, sekaligus menunjukkan betapa seriusnya mereka memandang permainan ini. Tentu saja, seiring berjalannya waktu, tradisi-tradisi ekstrem tersebut memudar.
Permainan muncang kembali menjadi milik rakyat. Namun aura persaingan yang melekat padanya tak pernah hilang. Di era kolonial, adu muncang masih sering terlihat dimainkan oleh anak-anak pribumi di halaman rumah, pekarangan, atau bahkan di sekolah-sekolah desa. Tidak hanya menghibur, permainan ini menjadi cara anak-anak belajar berkompetisi dan bersosialisasi secara alami.
Memasuki era modern, permainan adu muncang perlahan mengalami pergeseran fungsi dan bentuk. Jika dulu muncang menjadi bagian dari permainan spontan anak-anak di alam terbuka, kini muncang mulai dikenalkan ulang dalam bingkai budaya yang lebih terstruktur. Ia melakukan transisi menjadi salah satu bagian dari daftar permainan tradisional yang dikurasi secara resmi oleh lembaga-lembaga pelestari kebudayaan.
Adu muncang mulai dihadirkan kembali dalam gelaran seperti festival budaya lokal, perayaan Hari Anak Nasional, hingga program muatan lokal di beberapa sekolah dasar. Permainan ini tidak lagi sekadar alat bermain, melainkan menjadi media edukasi tentang warisan budaya Nusantara. Muncang yang dulu hanya ditemukan di bawah pohon kini dijadikan simbol kekayaan tradisi, dibingkai, bahkan dihadirkan dalam pertunjukan khas daerah.
BACA JUGA
Seren Taun ke-446 Kasepuhan Sinar Resmi Sukabumi: Tradisi Luhur Penguat Ketahanan Pangan dan Budaya
4 Nilai Strategis Kesenian Tarawangsa yang Masuk Kategori Warisan Budaya Takbenda
Perubahan ini menjadi penting, mengingat adu muncang menyimpan potensi besar dalam penguatan identitas lokal. Transisi dari permainan rakyat ke permainan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun ini juga menandakan kesadaran baru dalam melestarikan budaya.
Nilai-nilai seperti sportivitas, ketangguhan, dan kreativitas yang terkandung di dalamnya kembali diangkat, bukan hanya sebagai nostalgia masa kecil, tetapi juga sebagai bagian dari pendidikan karakter anak bangsa.
Kini, adu muncang mungkin tak lagi terdengar setiap hari di halaman-halaman rumah seperti dulu. Tapi dalam bentuk barunya sebagai permainan tradisional, muncang tetap berbicara: tentang sejarah, tentang kebudayaan, dan tentang bagaimana hal-hal kecil dari masa lalu bisa menjadi jembatan penting menuju masa depan yang lebih menghargai akar identitasnya sendiri.
(Daniel Oktorio Saragih/Magang/Aak)