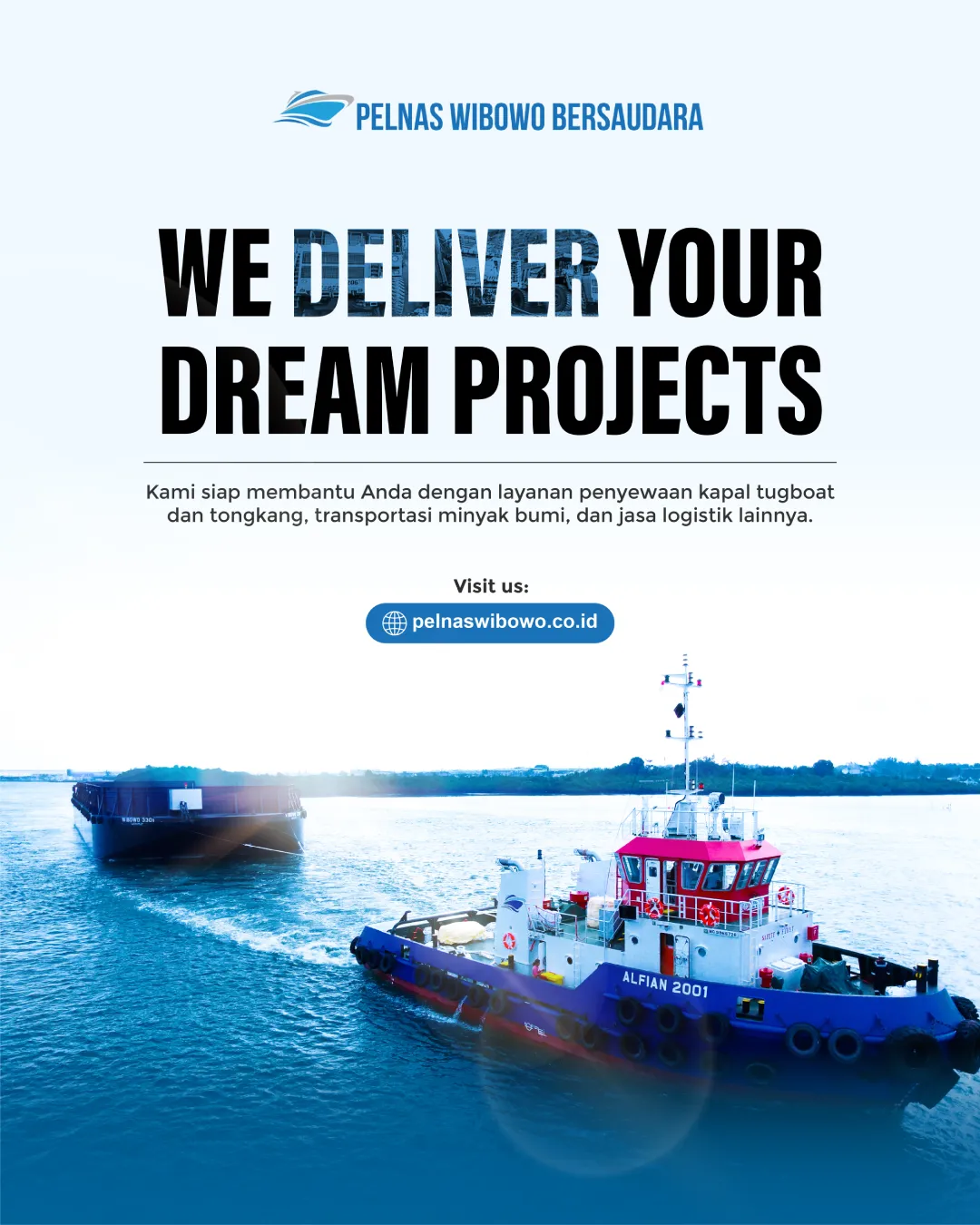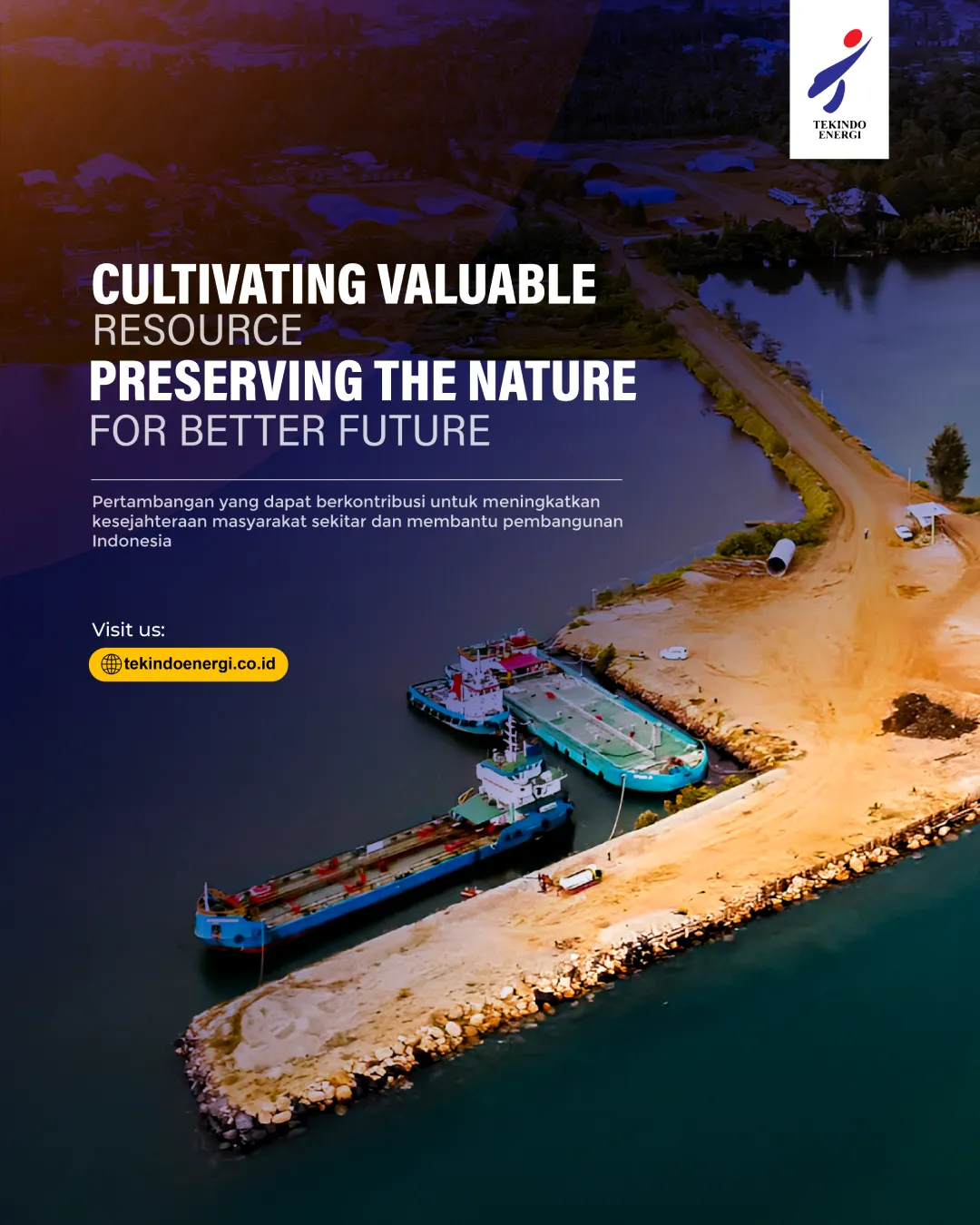BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Di tengah lanskap musik metal yang kerap dibanjiri oleh citra kegelapan, amarah, dan pemberontakan yang mentah, Ghost berdiri menjadi anomali yang justru merayakan kekacauan dengan keanggunan.
Di bawah kendali sang vokalis, Tobias Forge yang juga otak di balik figur Papa Emeritus dan Cardinal Copia, Ghost tidak hanya menghadirkan konser, tetapi semacam misa tandingan, sebuah “anti-liturgy” yang menggabungkan satire agama, glam rock, opera gelap, dan kritik sosial dengan bungkus seni visual kelas tinggi.
Fenomena Ghost tak bisa dipahami hanya dari riffs gitar atau chorus lagu seperti Year Zero atau Rats saja. Ia harus dibaca sebagai teks budaya yang berlapis-lapis, di mana estetika barok Gereja Katolik Roma diretas dan dibajak menjadi kendaraan untuk menyampaikan pesan tentang kekuasaan, patriarki, dan absurditas hierarki spiritual.
Dalam setiap penampilan panggung, Ghost tidak sekadar “bermain musik.” Mereka menampilkan ritual yang secara sadar mengolok-olok liturgi gereja, lengkap dengan mitra Paus, tongkat Ferula (diganti menjadi Grucifix), hingga prosesi ala misa. Namun, ini bukan sekadar gimmick. Forge tahu betul bahwa kekuatan agama tidak hanya ada dalam dogma, tetapi dalam simbol dan teatrikalitas.
Jika merujuk pada pemikiran Michel Foucault, kita tahu bahwa kekuasaan tidak selalu memaksa secara terang-terangan; ia bekerja lewat representasi dan struktur naratif yang mapan. Ghost dalam hal ini tidak serta-merta menghujat agama, tapi menelanjangi mekanisme kekuasaannya. Ketika Papa Emeritus berdiri di altar panggung, ia adalah kiasan dari seorang pemimpin spiritual sekaligus diktator budaya pop yang agung, karismatik, dan fiktif.
Kritik Sosial Lewat Figur Cardinal Copia
Di era Prequelle dan Impera, Tobias Forge memperkenalkan karakter Cardinal Copia sebagai antitesis dari “Papa” sebelumnya. Copia tidak datang dengan wibawa kekuasaan religius tapi ia canggung, lugu, penuh humor, bahkan kadang terlihat seperti karakter kartun. Namun di sinilah letak revolusinya.
Cardinal Copia adalah simbol generasi baru yang tidak lagi terjebak dalam narasi besar kekuasaan absolut. Ia adalah representasi manusia biasa yang mencoba mencari tempat dalam sistem yang absurd.
Dalam seni rupa kontemporer, kita bisa membandingkan Copia dengan karya-karya Cindy Sherman atau Gilbert & George yang menggabungkan kekonyolan dengan kritik sosial yang tajam melalui performativitas identitas.
Baca Juga:
Pentagon Pakai Lagu “Enter Sandman” Tanpa Izin, Metallica Geram Minta Takedown!
Konser Terakhir Black Sabbath “Back To The Beginning” Jadi Aksi Amal Terbesar Dalam Sejarah
Evolusi Perlawanan Lagu “Bella Ciao” dari Buruh ke Gerilya, dari Netflix ke Jalanan!
Estetika Visual: Antara Rococo dan Distorsi Pop
Secara visual, Ghost adalah kelompok seni rupa performatif. Panggung mereka penuh dengan arsitektur pseudo-gotik, vitral kaca palsu, obor api, dan pewarnaan pastel yang menyerupai gereja Eropa abad pertengahan jika dilukis oleh Salvador Dalí. Kostum para Nameless Ghouls yang kini berevolusi dari jubah anonim ke setelan tuksedo hitam ala silent film villains, menunjukkan bahwa Ghost tak pernah berhenti mengutak-atik konvensi.
Dalam hal ini, mereka mirip dengan gerakan camp yang dikaji oleh Susan Sontag: suatu bentuk ekspresi berlebihan yang secara sadar ‘palsu’ untuk menyoroti absurditas norma sosial. Ghost menegaskan bahwa dalam dunia yang terlalu serius, satu-satunya bentuk pembangkangan tersisa adalah dengan merayakan kekonyolan secara serius.
Relevansi di Dunia Sekular
Di era ketika agama tradisional mulai kehilangan pijakan, namun spiritualitas tetap dicari, Ghost hadir sebagai ruang aman bagi mereka yang tidak lagi ingin percaya tapi tetap merindukan upacara. Layaknya sebuah gereja bayangan, konser Ghost adalah tempat untuk memuja bukan Tuhan atau Iblis, tapi kemanusiaan yang rapuh dan penuh paradoks.
Kehadiran fans queer, non-biner, dan individu dari berbagai latar belakang marginal di konser-konser mereka menunjukkan bahwa Ghost telah menjadi semacam “tempat suci” yang tidak mengkhotbahkan keselamatan, tapi penerimaan. Mereka membalik konsep “iman” menjadi bentuk eksistensial yang bukan soal percaya pada dogma, tetapi percaya bahwa seni bisa menyelamatkan, walau hanya untuk satu malam.
Pada akhirnya, Ghost bukanlah tentang menyembah Setan sebagaimana yang sering dituduhkan kelompok konservatif. “Setan” dalam narasi mereka adalah metafora dari perlawanan terhadap otoritas yang beku dan moralitas yang dibuat-buat.
Mereka menampilkan mimbar tandingan, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengajak kita berpikir ulang: siapa yang sebenarnya kita sembah selama ini?
*Opini ini sepenuhnya merupakan pandangan penulis dan tidak mencerminkan kebijakan redaksi Teropong Media.
(Dist)