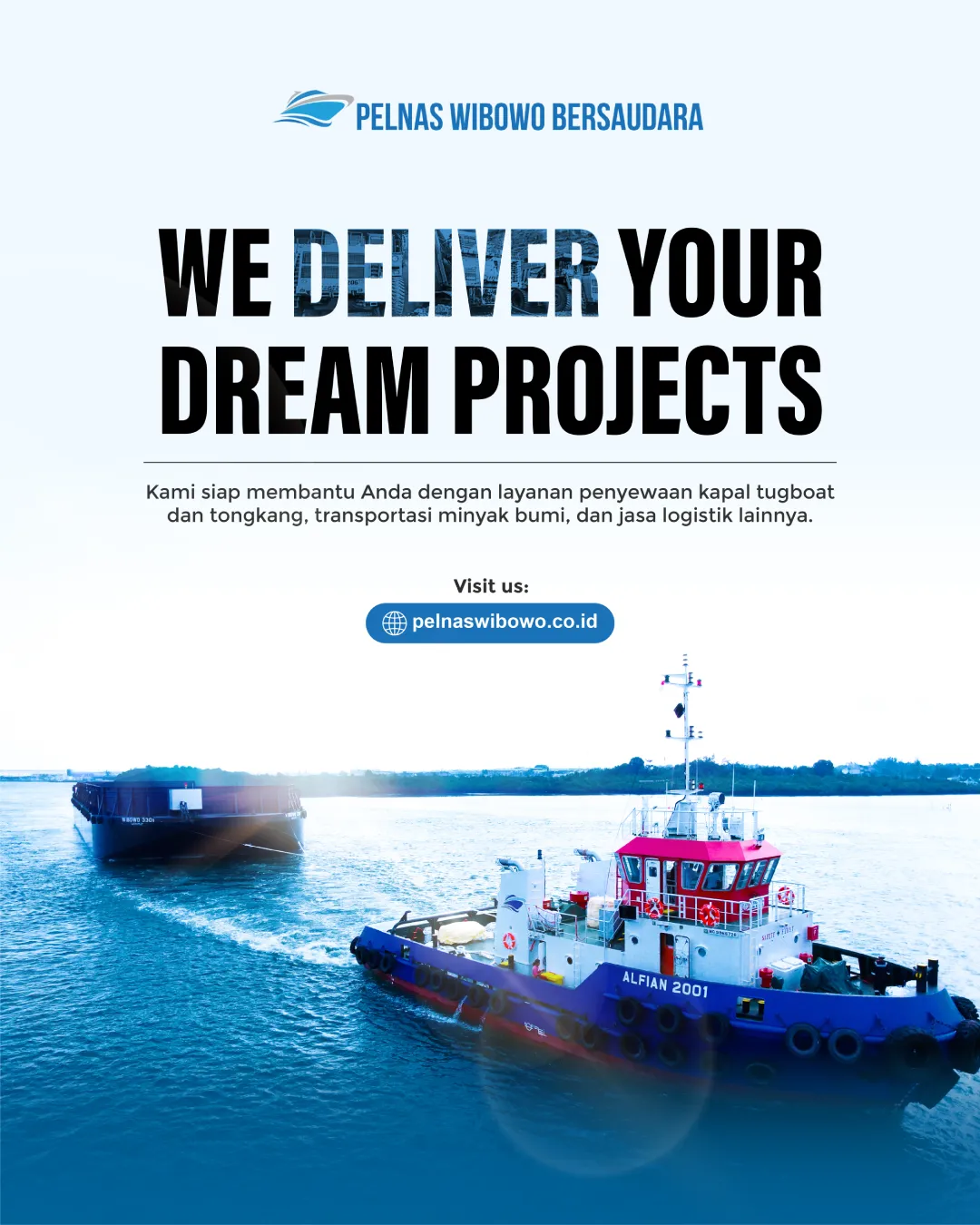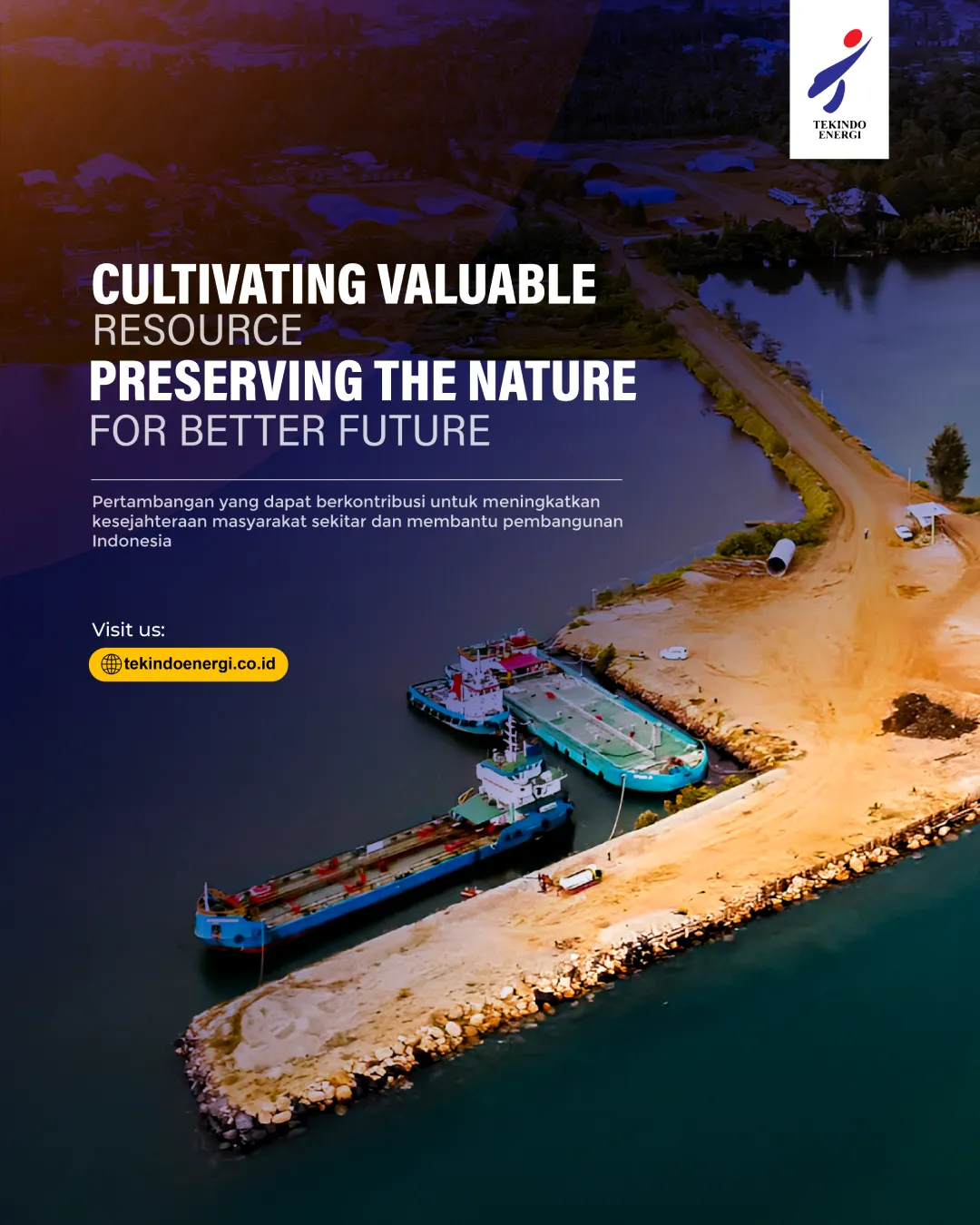JAKARTA, SUAR MAHASISWA–
Di dalam ruang kelas, para mahasiswa tengah duduk melingkar di atas lantai, saling bertatap muka dan berbincang. Sekilas tampak seperti kegiatan biasa, namun inilah salah satu bentuk ruang diskusi yang mulai langka: ruang dialektika—tempat bertukar gagasan dan pikiran diuji.
Mahasiswa kerap disebut sebagai agen perubahan, pilar logika, dan ujung tombak gerakan intelektual. Namun realita dan dinamika yang terjadi saat ini, muncul pertanyaan besar: di mana ruang-ruang dialektika yang dahulu menjadi nyawa kampus? Kini, opini lebih sering dibentuk dalam bentuk unggahan singkat dan komentar instan, ketimbang hasil perdebatan rasional yang lahir dari ruang diskusi. Padahal, sejarah perubahan sosial menunjukkan bahwa gerakan besar selalu dimulai dari ruang kecil yang penuh pertukaran gagasan.
Fenomena ini menunjukkan kemunduran dalam budaya berpikir kritis. Ruang diskusi tatap muka perlahan digantikan oleh debat kusir di ruang digital, yang lebih mementingkan emosi daripada logika. Kecepatan informasi justru mempersempit ruang refleksi. Mahasiswa semakin jarang terlibat dalam dialog mendalam, karena terbiasa pada konten yang cepat dikonsumsi dan mudah dilupakan. Akibatnya, kemampuan untuk mengelola argumen secara runtut dan logis ikut tergerus.
Di tengah kecenderungan tersebut, masih terdapat titik-titik harapan. Beberapa komunitas mahasiswa masih berinisiatif menciptakan ruang diskusi sederhana. Dalam lingkaran duduk yang tidak formal, terjadi pertukaran ide yang bebas nilai, tanpa tekanan status atau jabatan. Kegiatan seperti ini mencerminkan bahwa budaya dialektika belum sepenuhnya punah. Masih ada ruang untuk menyemai logika, mendengar perbedaan, dan melatih argumentasi yang sehat.
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hambatan tetap ada. Tidak semua mahasiswa memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapatnya di ruang terbuka. Budaya takut salah, kurangnya fasilitator, dan minimnya literasi diskusi menjadi tantangan serius. Diskusi yang tidak terarah juga berisiko melahirkan pembicaraan dangkal, tanpa substansi yang jelas. Belum lagi ketimpangan partisipasi yang menyebabkan ruang diskusi hanya diisi oleh segelintir suara dominan.
Meski begitu, ancaman akan tetap selalu membayangi. Budaya polarisasi, “cancel culture”, serta kecenderungan menolak pendapat yang berbeda tanpa dialog rasional telah meracuni banyak ruang publik. Kritik dianggap serangan pribadi, dan perbedaan dianggap sebagai bentuk permusuhan. Tanpa ruang aman untuk berpendapat, generasi muda berisiko tumbuh tanpa kepekaan berpikir, dan tanpa keterampilan berdialektika yang sehat.
Menjaga hidupnya ruang diskusi adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak harus selalu dalam bentuk seminar besar atau forum ilmiah. Cukup dengan duduk melingkar, saling mendengar, dan saling mempertanyakan. Dari ruang sederhana seperti itu, kekuatan berpikir kritis dapat dibangkitkan kembali. Karena ketika ruang dialektika mati, maka nalar perlahan ikut terkubur, dan masa depan menjadi tak lebih dari sekadar gema opini kosong.
Foto ini bukan sekadar potret sekelompok mahasiswa yang sedang berkumpul. Ia adalah simbol perlawanan terhadap sunyinya ruang diskusi yang bermakna. Di tengah dunia yang makin riuh dan serba instan, kita butuh lebih banyak ruang seperti ini—ruang untuk diam sejenak, mendengar, dan berpikir ulang, agar daya kritis kita tidak sepenuhnya pupus.
( Fajar Novryanto, Universitas Persada Indonesia Y.A.I )