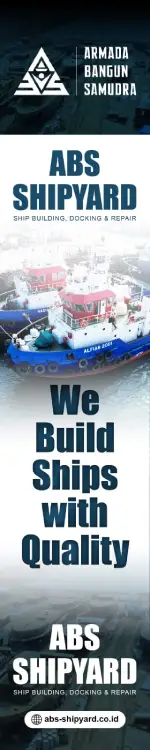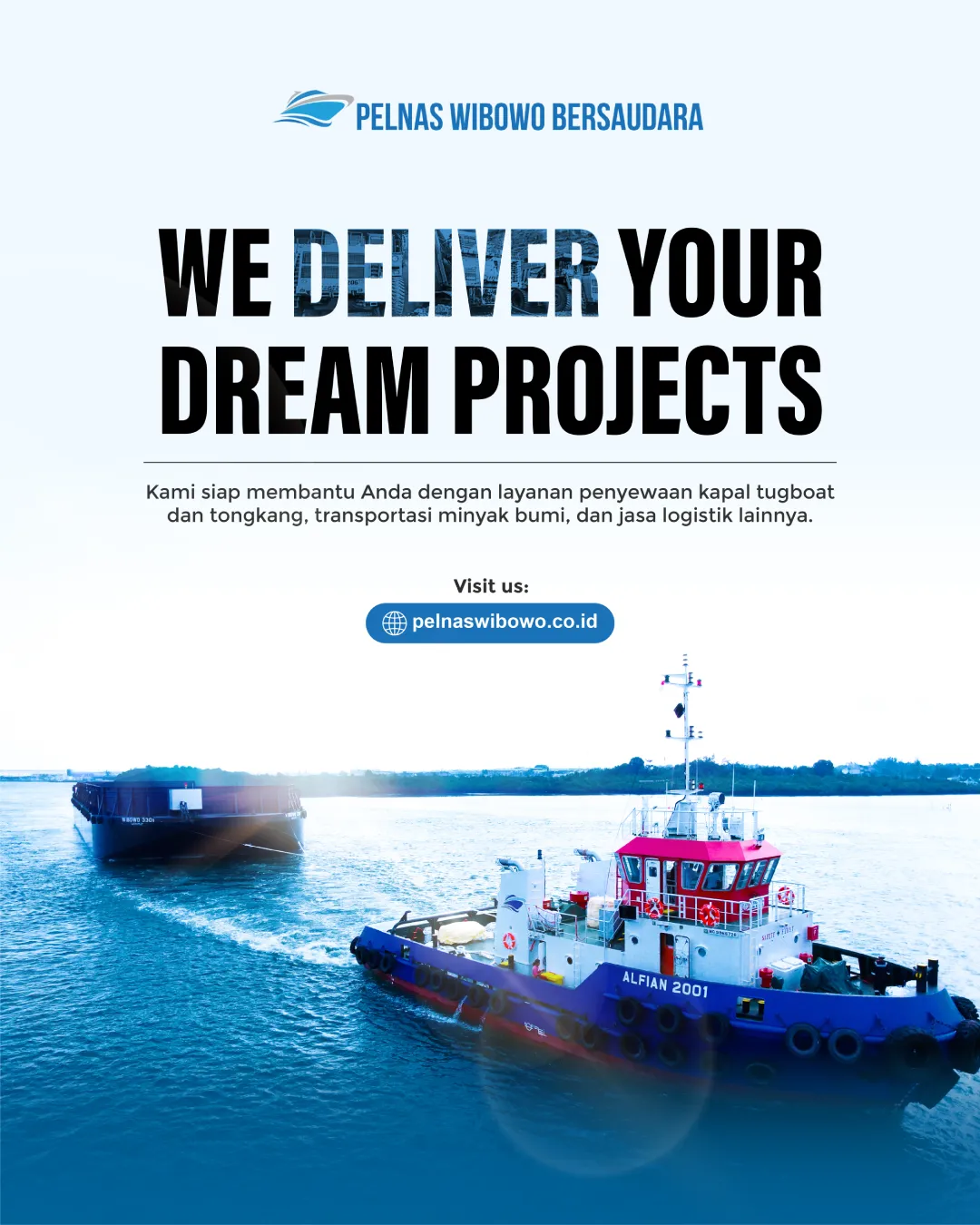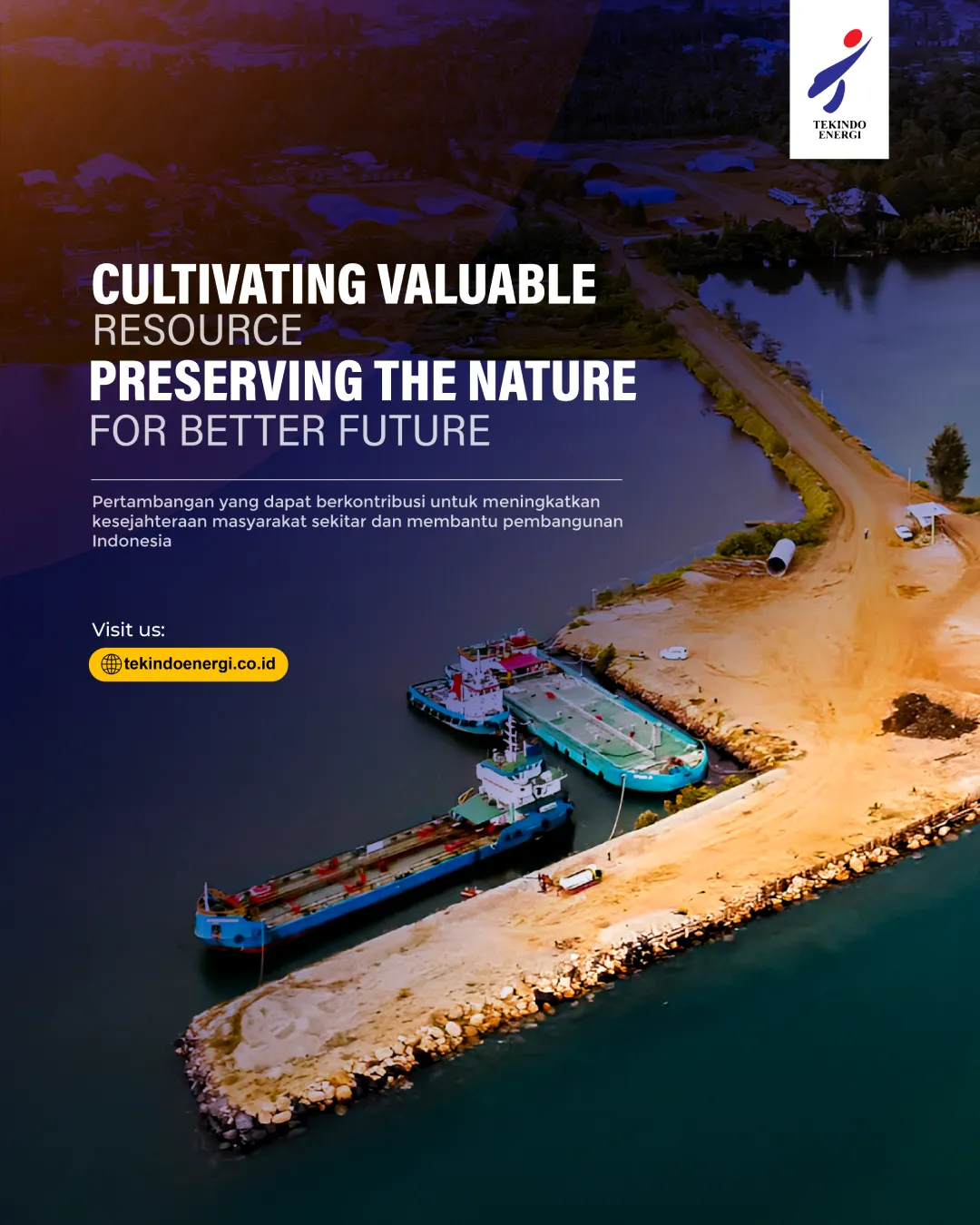GARUT, TEROPONGMEDIA.ID — Kesenian tradisional Badeng muncul pada tahun 1800 di Desa Sanding, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, tepatnya pada masa Para Wali.
Mengutip laman Kemendikbud RI, kesenian Badeng pertama kali dikembangkan oleh seorang penyebar agama Islam bernama Arfaen Nursaen yang berasal dari Banten dan kemudian menetap di Desa Sanding, yang kemudiania dikenal dengan sebutan Lurah Acok.
Lurah Acok memikirkan cara agar ajaran Islam dapat tersebar luas di masyarakat, mengingat pada waktu itu agama Islam masih sangat asing.
Suatu hari, saat ia pergi ke sebuah perkampungan di Malangbong, di tengah perjalanan ia menemukan sebuah benda berbentuk panjang dan bulat terbuat dari bambu serat.
Tanpa berpikir panjang, ia membawa benda itu pulang dan mengubahnya menjadi alat yang dapat mengeluarkan bunyi.
Kemudian, Arfaen mengumpulkan para santrinya dan meminta mereka membuat alat-alat lain dari bambu tua untuk menciptakan harmoni suara dengan alat yang telah ia buat.
Bambu-bambu itu disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan suara nyaring. Ketika semua alat itu dimainkan, terciptalah irama musik yang enak didengar, dipadukan dengan nyanyian berirama Sunda Buhun dan Arab atau Solawatan.
Badeng sebagai Media Syiar Islam
Sejak saat itu, Lurah Acok dan para santrinya rutin berkeliling mengumpulkan tokoh masyarakat, umaro, dan santri untuk bermusyawarah sambil mengenalkan ajaran Islam melalui tabuhan alat-alat musik tersebut.
Mereka membawakan lagu-lagu Solawatan dan Sunda Buhun yang syairnya mengajak masyarakat memeluk agama Islam.
Hampir seluruh penduduk Desa Sanding, kampung-kampung sekitar, hingga wilayah Malangbong dan daerah lain di Kabupaten Garut yang pernah dikunjungi Lurah Acok akhirnya memeluk Islam.
Sejak itulah, Lurah Acok menamakan kesenian ini “Badeng,” yang berasal dari kata “Bahadrang,” artinya musyawarah atau berunding dengan iringan kesenian. Badeng menjadi sarana penyebaran Islam pada masa itu.
Hingga kini, kesenian Badeng masih bertahan dan digunakan sebagai hiburan, penyambutan tamu penting, perayaan Mauludan, khitanan, hajatan, dan acara lainnya. Namun, para pemainnya kebanyakan sudah berusia lanjut, rata-rata sekitar 60 tahun.
Alat-alat musik dalam kesenian Badeng terdiri dari:
- 2 Angklung Kecil (Roel): Melambangkan persatuan antara ulama dan umaro (pemerintah), dimainkan oleh seorang dalang.
- 2 Dogdog Lonjor (Ujungnya Simpay Lima): Melambangkan keseimbangan dunia (siang-malam, laki-perempuan), dimainkan oleh dua orang. Simpay lima melambangkan rukun Islam.
- 7 Angklung Agak Besar: Terdiri dari angklung indung, angklung kenclung, dan angklung kecer, disesuaikan dengan nama-nama hari, dimainkan oleh empat orang.
Sementara itu merujuk pada narasi di kanal YouTube Desa Sanding, berdasarkan penuturan tokoh seni Badeng di Desa Sanding, tidak ada catatan secara spesifik mengenai tahun kelahiran kesenian ini.
Namun, diperkirakan pada abad ke-17, kesenian Badeng sudah muncul di Kampung Sukabatu, Desa Sanding, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut.
Pada masa itu, sebagian besar penduduk setempat masih menganut agama Hindu dan Buddha, sehingga budaya mereka pun banyak dipengaruhi oleh kedua agama tersebut.
Untuk menyebarkan agama Islam di daerah ini, para penyebar agama menggunakan kesenian Badeng sebagai sarana menarik minat masyarakat.
Mereka mengumpulkan dan menghibur warga dengan pertunjukan Badeng sambil mengenalkan ajaran Islam.
BACA JUGA
Ronggeng Ketuk, Kesenian Khas Indramayu di Ambang Kepunahan
Kuda Renggong: Kesenian Unik dari Sumedang yang Wajib Dilestarikan
Asal Kata Badeng
Nama “Badeng” diambil dari kata “Badi’un” dan “Bahadreng,” yang berarti bermusyawarah. Dalam lagu-lagu yang dibawakan, banyak terdapat kata-kata berbahasa Arab, terutama kalimat-kalimat yang biasa digunakan dalam istilah keislaman.
Tujuannya adalah agar masyarakat saat itu tertarik dengan bahasa Arab, khususnya bahasa yang digunakan sebagai pengantar dalam memeluk agama Islam.
(Aak)