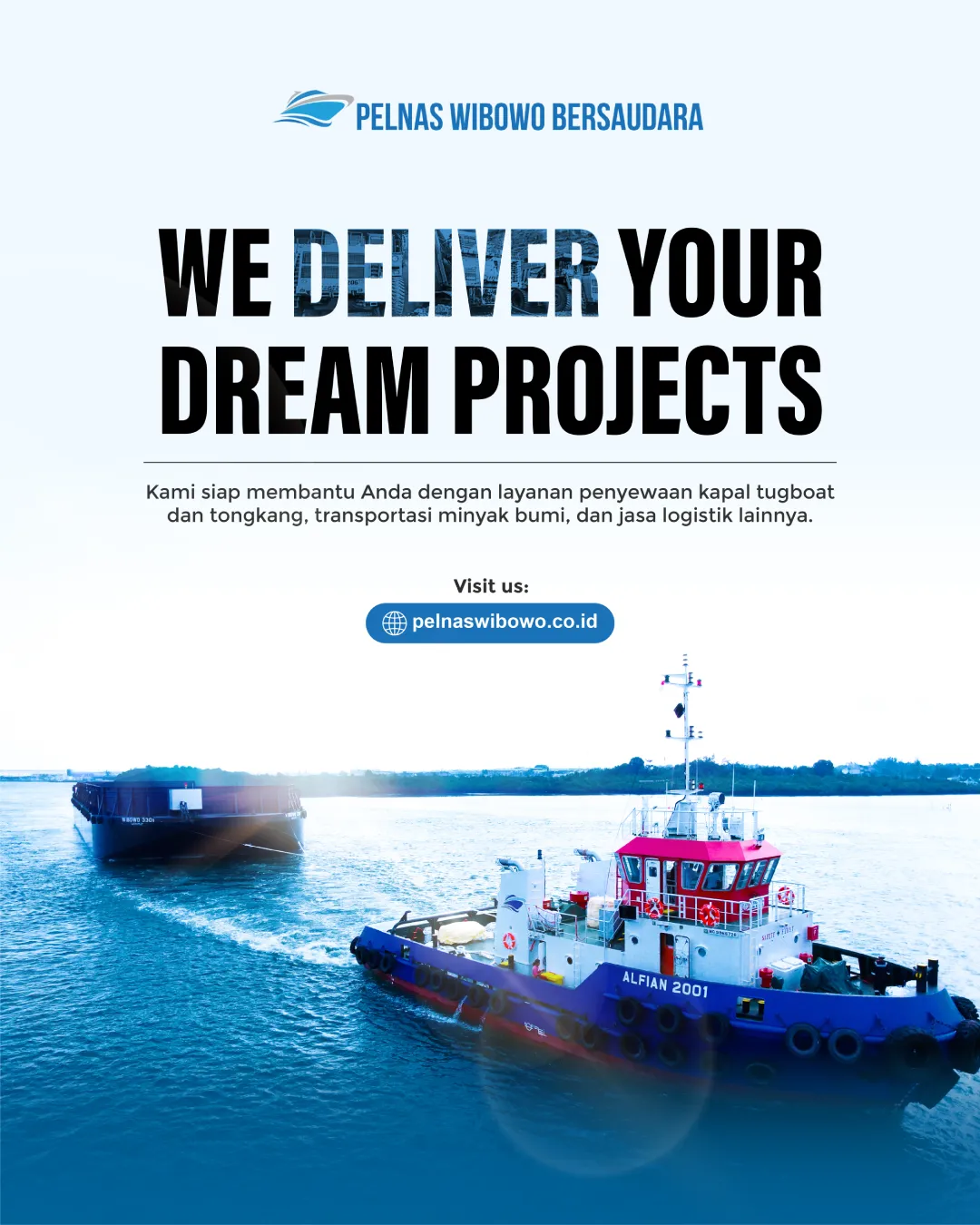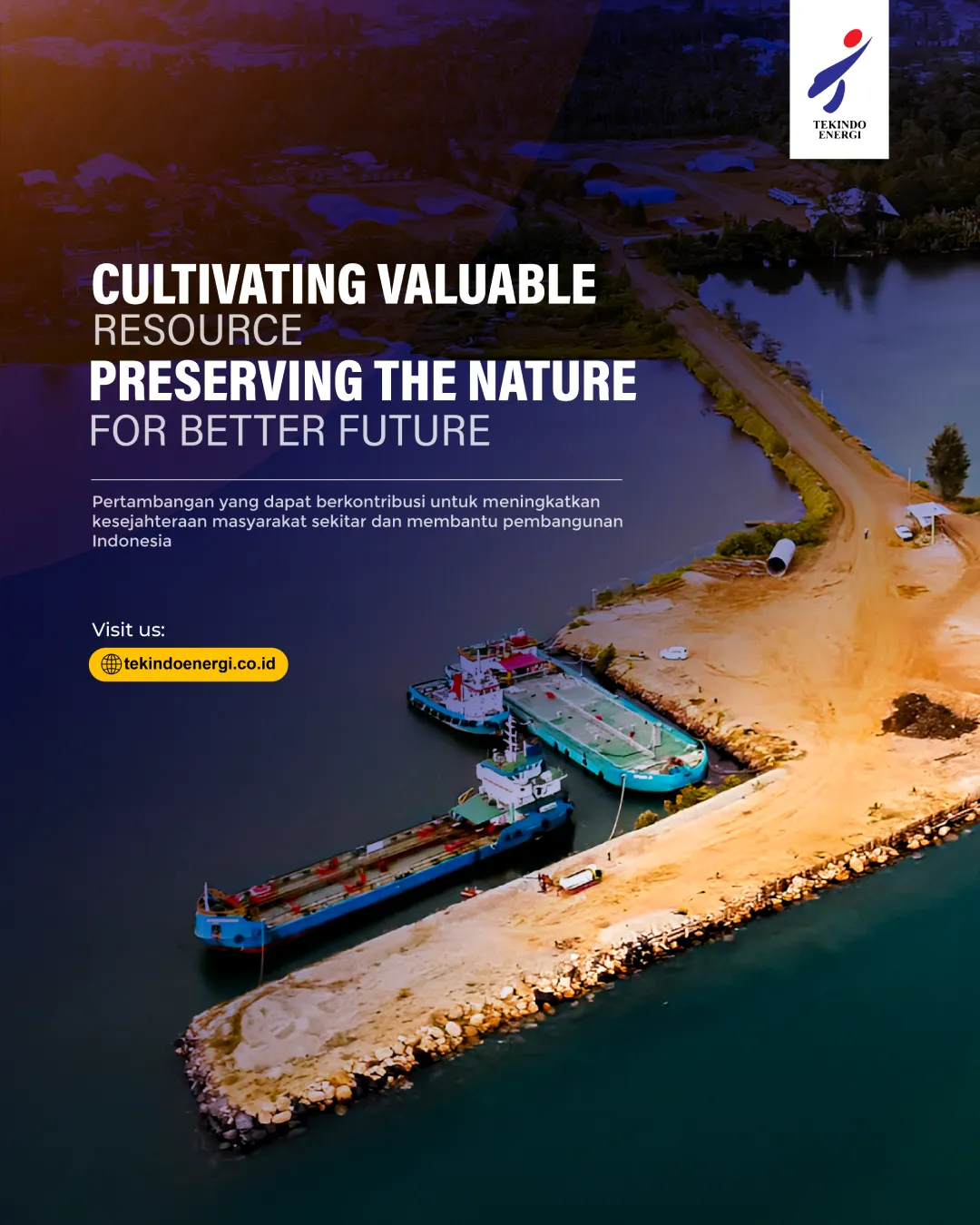BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Dalam dentuman kendang yang menggema dan sorakan penonton yang antusias, Benjang kembali menjadi suguhan khas masyarakat Ujungberung. Namun di balik pertunjukan yang hari ini memukau banyak orang, kesenian ini menyimpan sejarah kelam: sebuah masa ketika Benjang tidak hanya disingkirkan, tetapi dilarang secara aktif oleh kekuasaan.
Benjang merupakan seni bela diri tradisional asal Ujungberung, Kota Bandung. Ia memadukan teknik pencak silat dengan unsur hiburan dan pertunjukan rakyat. Biasanya digelar dalam momen-momen penting masyarakat seperti panen raya, khitanan, atau syukuran. Kesenian ini tidak hanya memperlihatkan kekuatan fisik, tetapi juga menampilkan nilai-nilai spiritual, keberanian, dan persaudaraan khas masyarakat Sunda.
Namun, di masa Orde Baru, sekitar tahun 1970-an hingga akhir 1990-an, Benjang masuk dalam daftar kesenian yang dilarang tampil secara terbuka. Pemerintah kala itu menilai bahwa Benjang mengandung potensi kekerasan dan berisiko menimbulkan kerusuhan sosial. Dalam Jurnal Budaya Etnika, Wahyuni, A. P., Lahpan, N. Y. K., & Yuningsih, Y. (2021) menyatakan bahwa pemerintah menganggap atmosfer kompetitif dalam pertunjukan Benjang dapat memicu konflik antarkelompok masyarakat. Kegiatan yang menarik kerumunan besar, penuh sorakan, dan diwarnai adu fisik dianggap sebagai pemantik ketegangan di tengah masyarakat yang saat itu dijaga ketat dalam narasi stabilitas dan ketertiban.
Baca Juga:
Masih Dianggap Mistis, Ini Sisi Lain Kesenian Reak yang Jarang Diungkap
4 Nilai Strategis Kesenian Tarawangsa yang Masuk Kategori Warisan Budaya Takbenda
Pelarangan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi berimbas langsung pada kehidupan komunitas. Organisasi-organisasi Benjang dibubarkan secara paksa, pelatihan ditiadakan, dan pertunjukan dilarang keras. Para pelatih kehilangan murid, dan anak-anak muda kehilangan kesempatan belajar tradisi yang telah hidup ratusan tahun. Dalam kondisi ini, Benjang hanya bertahan di ruang-ruang tersembunyi: di kebun, ladang, atau halaman rumah tertutup. Aktivitas dilakukan diam-diam, penuh risiko, hanya demi menjaga agar nyala tradisi ini tidak benar-benar padam.
ampir tiga dekade lamanya, Benjang tidak memiliki tempat di ruang publik. Akibatnya, sebagian besar praktik dan teknik dalam kesenian ini tidak terdokumentasi dengan baik. Banyak nilai-nilai luhur yang terkandung dalam gerak dan ritual Benjang hilang bersama dengan generasi yang terputus. Stigma negatif pun muncul. Sebagian masyarakat mulai menganggap Benjang sebagai kegiatan kasar, tidak mendidik, dan bahkan berbahaya.
Setelah masa reformasi tahun 1999, iklim kebebasan berekspresi mulai memungkinkan kebangkitan kembali kesenian-kesenian lokal yang selama ini dibungkam. Komunitas Benjang yang semula tersembunyi perlahan bangkit kembali. Mereka membentuk ulang organisasi pelestari, menyusun program pelatihan bagi generasi muda, serta mengadakan pertunjukan dalam skala kecil yang lama-lama diterima kembali oleh publik.
Hamid (2022), dalam penelitiannya mengenai perkembangan organisasi Benjang, menyebutkan bahwa pada awal 2000-an komunitas Benjang Gulat Ujungberung kembali aktif, menandai era baru kebangkitan kesenian ini. Upaya pelestarian diperkuat melalui pelatihan terstruktur, kerja sama dengan sekolah, hingga keikutsertaan dalam festival budaya yang lebih besar. Dukungan dari pemerintah daerah pun mulai hadir, seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya lokal.
Meski larangan telah usai, dampaknya masih terasa hingga hari ini. Minimnya dokumentasi, terbatasnya jumlah pelatih senior, serta belum adanya pengakuan formal dalam sistem pendidikan menjadi tantangan tersendiri. Benjang memang telah kembali, tetapi perjuangan untuk mengangkatnya ke posisi sejajar dengan kesenian lain masih membutuhkan komitmen dan kerja keras dari berbagai pihak.
Kisah Benjang menjadi bukti nyata bagaimana sebuah kesenian tradisional bisa menjadi korban dari persepsi kekuasaan yang mengaitkan ekspresi budaya dengan ancaman stabilitas. Padahal, di balik gerakan adu fisik yang tampak keras, Benjang menyimpan nilai-nilai luhur seperti sportivitas, solidaritas, dan penghormatan terhadap leluhur.
Kini, Benjang tampil kembali di tengah masyarakat, namun sejarah kelam pelarangannya patut dikenang. Bukan untuk membuka luka lama, tetapi sebagai pengingat bahwa warisan budaya tak selalu berada dalam posisi aman. Ia bisa ditekan, dibungkam, dan dilupakan, jika tak ada yang memperjuangkan keberadaannya. Benjang berdiri hari ini bukan karena semata dilestarikan, tetapi karena selama masa gelapnya, ada komunitas kecil yang tak berhenti menjaga nyalanya dalam diam.
Penulis:
Daniel Oktorio Saragih
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia (UNIBI)