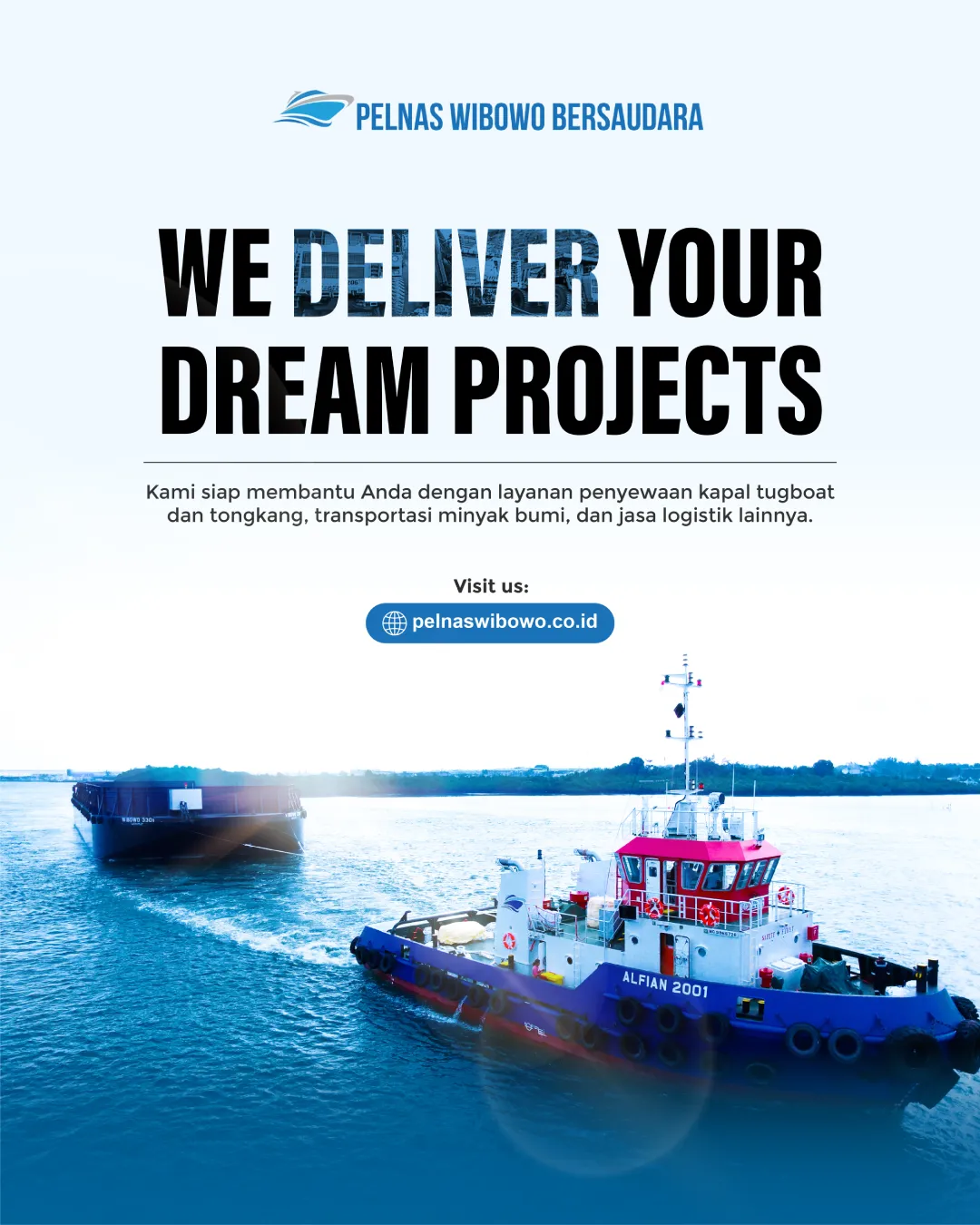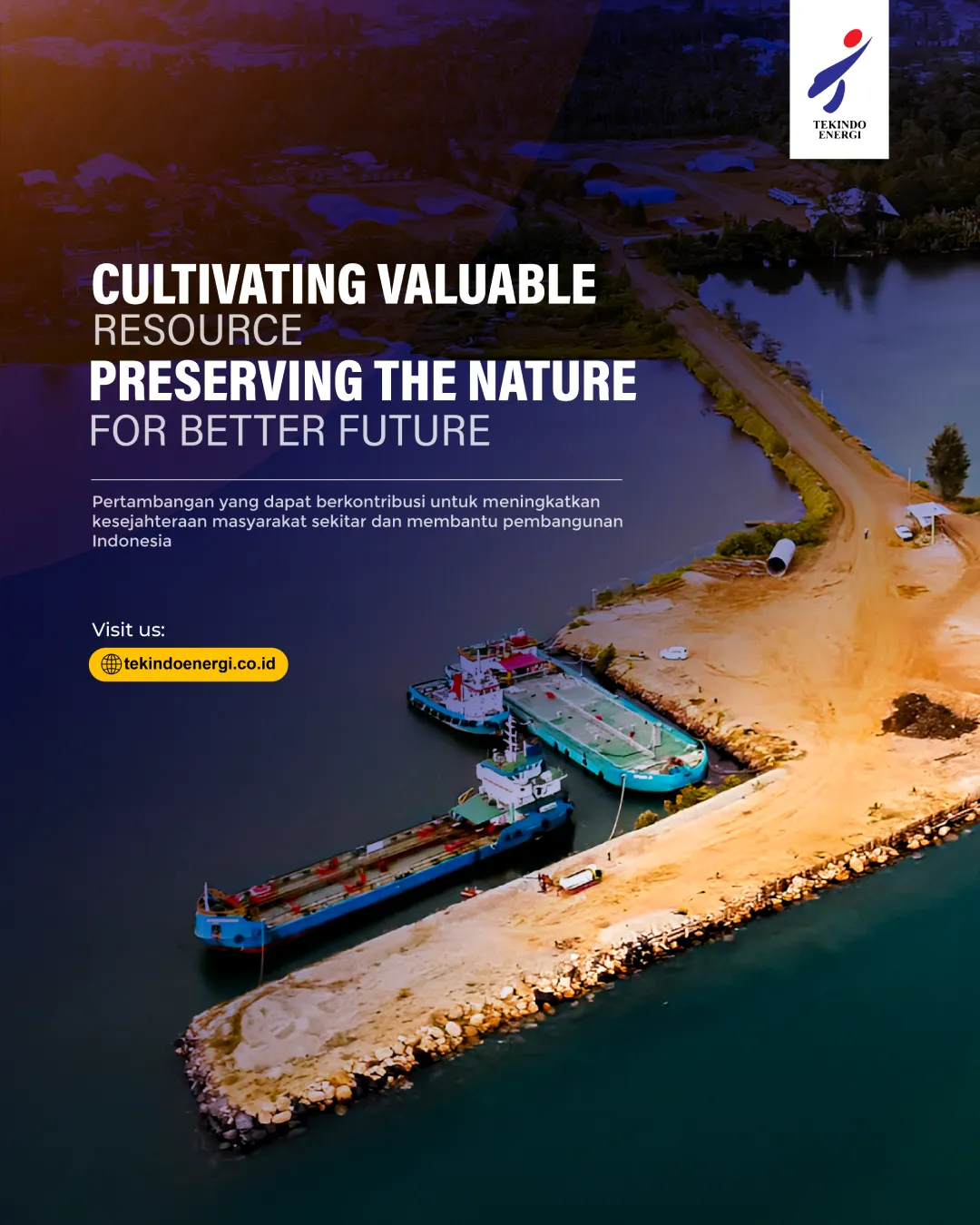BANDUNG,TM.ID: Blues merupakan sebuah wacana yang berpotensi dapat membuka kemungkinan-kemungkinan materi bagi siapapun untuk dapat berkontribusi di dalamnya secara kompleks. Sebagai akar musik modern Afro-Amerika, blues melahirkan banyak dunia narasi, dari kegelapan kaum kulit hitam, definisi spirit harapan, teknik-teknik penyajian musikal, hingga pergerakan dalam berbagai medium termasuk identitas visual.
Musik sebagai bahasa rasa dan pikir(an), di mana sebagai reflektor terbaik yang mampu saling memberi “dunia” antara pelaku dan apresiatornya. Saling menginterpenetrasi melalui media indrawi, sebuah getaran yang hadir sebagai peran pengganti peristiwa abstrak. Gairah yang mendalam dari sebuah pengalaman atau peristiwa buruk, sebuah sejarah kelam yang mampu bertransformasi untuk “hadir” secara estetik, dari sebuah ungkapan spirit harapan melalui langgam berbunyi, kemudian bertransformasi menjadi sebuah pesta dengan gemuruh distorsi di ruang pertunjukan. Pada dasarnya spirit tersebut adalah bentuk ragam dari sebuah bahasa itu sendiri, baik secara instrumental, gelombang warna vokal maupun keganasan lirikal.
Dalam jalur eksistensinya, blues di Indonesia tumbuh menjamur di banyak belahan kota-kota di Indonesia seperti jakarta, Medan, Yogyakarta, Samarinda, sekitar Bali, Garut, Bogor, Tasik, Cirebon, Sukabumi, Bandung dan masih banyak lagi. Ada yang berdiri secara individu, juga tak sedikit yang beratap pada payung-payung komunitas. Layaknya komunitas secara umum, atas nama solidaritas, komunitas menampung penggemar, pemusik, kritikus, artworker, kolektor, muda-tua, band lawas dan baru, punya karya atau tidak, semua dalam satu wadah.
Termasuk bagaimana pembahasan ini diangkat, ketika saya membuka sedikit diskusi kecil bersama Kang Hadi Pramono, seorang pengamat, kolektor dan pemilik perpustakaan Blues di Bandung, serta penyiar Blues Mara di Radio Mara dari tahun 1990-2016 dan juga penyiar Radio Sonora di tahun setelahnya hingga terputus momen Covid lalu.
Secara sederhana dalam kacamata keilmuan Desain Komunikasi Visual, perannya bisa dilihat bagaimana media poster mampu hadir sebagai sarana informasi dan memunculkan minat audiens melalui komponen visual. Di luar itu, keterlibatan keilmuan DKV juga dapat terlihat saat kreator visual merepresentasikan intensitas makna pada serangkaian lagu atau album melalui karya-karya visualnya, seperti yang terkemas dalam cover album, single dan juga video klip.
Bagi pergerakan sampul lagu/album sendiri, memang ini bukan gerakan baru, secara luaran di awal kemunculannya kita bisa melihat sampul lagu hanya memperkenalkan nama musisi dan label rekamannya. Seperti sampul lagu milik Rodgers & Hart yang dirancang secara grafis oleh Alex Steinweis pada tahun 1939 di bawah Columbia Records. Lalu bagaimana dengan Blues? Menurut Kang Hadi Pramono sangat sulit untuk melacaknya, mengingat industri rekaman hanya menelurkan single-single saja dari tahun 1920-an.
Untuk mengurai itu, perlu sedikit diketahui bahwa pada era tahun 1920-1940-an teknologi penyimpanan lagu melalui plat/cakram/piringan hitam yang daya muat pemutarannya masih berkapasitas 78 Rpm (rotation per minute), yang berarti belum mampu memuat banyak lagu atau lagu-lagu berdurasi panjang. Oleh karenanya para musisi terutama blues, biasanya hanya merilis 2 lagu (setiap satu sisi cakram memuat 1 lagu; masing-masing berdurasi maksimal 3 menit). Hingga kemunculan PH 45 Rpm dengan ukuran yang lebih kecil namun tetap dengan kapasitas yang sama.

Dalam dunia Blues sendiri, di era 1920 hingga 1930-an selain cover dari katalog label rekaman Race Record yang fokus merekam musik-musik kalangan Afro-Amerika, hampir tidak ditemukan atau sulit untuk dilacak keberadaan sampul lagu dengan profil musisinya.
Sejauh ini, hipotesis mengarah bahwa pada sebagian umum musik Blues tampil di pasar industri tanpa sebuah desain di sampul, yang ada hanyalah brand label rekaman dan nama musisi yang melekat pada bagian tengah cakramnya. Meski begitu, melalui alat yang sederhana, Blues secara bersamaan muncul dengan keanekaragamannya seperti: Delta Blues yang dicurahkan oleh sang legendaris asal Missisipi – Robert Johnson, Jazz Blues yang sering dimainkan oleh Mamie Smith, Rag Blues-Memphis Blues yang kerap dibawakan oleh The Nite Owls dan sejenisnya yang masih dalam koridor tradisional.

Hal tersebut serupa terjadi di era tahun 1940 hingga 1960-an, industri musik tidak memiliki alasan yang jelas untuk menerangkan ketidakterlibatannya dalam mengekspos musisi kulit hitam dalam cover single-nya. Namun yang menarik di sini adalah peran majalah musik seperti Billboard, Cash Box, Rhytm & Blues, dan Variety yang mengulas kualitas musik-musik tersebut sebagai bentuk respon atas kegelimangan musik Afro-Amerika: Jazz, Blues, Gospel. Apa yang disampaikan ialah sebuah kritik atas kemenangan minoritas melalui jalur populer, dan kemudian Blues menjadi membudaya.
Mungkin ada segelintir musisi yang tidak terekspos secara visual, namun keberanian itu mulai terlihat pada single Lightnin’ Hopkins pada tahun 1959 dengan sentuhan Pop Art oleh Ronald Clyne yang terpengaruh Andy Warhol. Atau single berjudul “Have Guitar will Travel” milik Bo Didley dengan menggunakan Vespa yang dikemas dalam fotografi pada tahun 1960, yang juga beriringan dengan album konser milik Muddy Waters saat tampil di Newport Jazz Festival 1960. Dalam skala album rekaman yang utuh dipelopori oleh Junior Wells di tahun 1965 yang juga turut memunculkan profil tubuh/wajahnya.
Sebagai catatan, ada pula beberapa album yang mengkompilasi karya-karya yang tercecer dari musisi-musisi blues di era 1920-1950an. Seperti sampul populer yang muncul di tahun 1961, ketika album kompilasi Robert Johnson yang dirancang oleh sentuhan lukis Burt Goldblatt yang mengesankan karena berdampingan dengan isu perjanjian Faustian dan kematian (terbunuh) Johnson dengan iblis. Yang juga diikuti kemudian oleh banyak musisi, seperti lukisan dalam album Bill Bronzy di tahun yang sama, dan lain-lain.
Penyajian fotografi sendiri yang terterap dalam cover diikuti oleh beberapa musisi lainnya yang menampilkan karya kompilasi seperti album John Lee Hooker dan Fred McDowell, maupun kemunculan musisi blues baru dengan format album, seperti Buddy Guy, Jimmi Hendrix, dan sebagainya, termasuk yang dilakukan oleh segelintir musisi Blues dan Rock ‘n Roll kulit putih, seperti John Mayall & Blues Breakers bersama Eric Clapton, Johnny Winter, Allman Brothers, Rolling Stones dan masih banyak lagi.
Bagi jalur populer ini hal yang lumrah, namun akan berbeda jika studi diletakkan pada musisi kulit hitam. Saat musik Blues sebagai cikal bakal musik modern Amerika muncul, di sana akan ditemukan alasan-alasan mengapa cover album pada saat itu lebih didominasi pengeksposan wajah atau karakteristik tubuh musisinya untuk terpampang di sampul-sampul album.
Sistem perbudakan yang diterima oleh kaum Afro di negara-negara Eropa dan Amerika berhasil mendesak mereka (kulit putih) melalui jalur industri, agar (kulit hitam) dapat keluar dari penindasan masal melalui jalur popularitas. Kualitas musikal mampu mendorong industri untuk dapat menerima keberadaan dirinya. Ini bukan jalan yang mudah, persaingan dunia rekaman pada era 1920-1970-an bukan hanya menyoali kualitas musik-musik modern Amerika saja, namun isu rasis selalu dekat terjadi di antara mereka.
Nyatanya, fenomena-fenomena tersebut terlahir dari para musisi kulit hitam yang terbilang familiar di kalangan dunia blues. Hingga mungkin mengantarkan pada satu kesadaran bahwasanya popularitas musik modern terbangun atas sebuah nilai-nilai kelam.
Rasa pedih, kesepian seorang Hobo, kekejaman perbudakan, spiritualitas kepaganan, jeritan-jeritan rasial berhasil diangkat menjadi sebuah komoditas industri, dengan menampilkan kelayakan kaum Afro-Amerika dalam dunia musik yang terkemas dalam medium identitas visual. Teknik fotografi sengaja dihadirkan agar audiens bukan hanya sekadar mengenal musisi tersebut, melainkan mempunyai tujuan untuk mencapai kedekatan emosi dalam sejarah panjang yang gelap.
Jika ini dianggap sebagai bentuk pemberontakan, bisa jadi dapat dibenarkan. Terlebih diperkuat oleh para musisi kulit putih yang mulai gencar berkolaborasi dengan idola mereka (musisi blues kulit hitam) untuk tampil baik dalam bentuk album maupun panggung konser atau televisi.

Waktu demi waktu merubah citra musik blues, dari segi musik atas kemajuan teknologi, blues yang semula dimainkan dengan cara yang murung, perlahan menjadi sebuah musik pesta seperti warna musik Chicago Blues yang memiliki beat yang riang. Atau menjadi musik yang terdengar lebih garang ketika dimainkan oleh beberapa musisi kulit putih dengan gaya Texas Blues-nya. Atau musik-musik blues berirama cepat seperti yang dilakukan Chuck Berry, The Beatles, The Animals dan Rolling Stones dengan gaya Rock n Roll. Atau yang dipenuhi distorsi kotor seperti yang dilakukan Jimmi Hendrix, bahkan blues dalam porsi yang sangat kencang dalam nuansa Heavy Metal seperti yang dilakukan Motörhead.
Namun, tidak ada definisi pasti dalam kemeriahan bentuk-bentuk tersebut selain sebagai bentuk ekspresi kaum yang tertindas atau sekadar ekspresi empati yang pada akhirnya menambah khasanah jenis musik di hari ini.
Tentu musik tidak berdiri sendiri, apa yang ingin diluapkan kemudian adalah bentuk yang terlihat, bagaimana musik hadir dalam bentuk kemasan album, gaya berpakaian hingga gaya hidup. Sekarang kita bisa mulai menerka bahwa musik Rap, Hip-hop dan semacamnya tampil secara mencolok, dengan kalung emas dengan ikon Dolar sebesar buah kelapa dalam sebuah video klip, bergelimangan mobil mewah, wanita berbikini dengan sisi erotis, gaya berbicara yang ekspresif, tak lain merupakan bentuk pemberontakan dari masa lalunya.
Di Indonesia sendiri bisa disebut terkena dampak dari apa yang disajikan sejak industri masa lalu (1950-an) sampai hari ini, baik apa yang terkemas oleh musik Blues secara langsung, maupun imbas dari era psychedelic yang sangat meledak di masanya, hingga keanekaragaman yang terjadi hari ini, seperti kemunculan musisi-musisi Blues di Indonesia yang patut ditelusuri.
(Moch. Ficky Aulia/Dist)