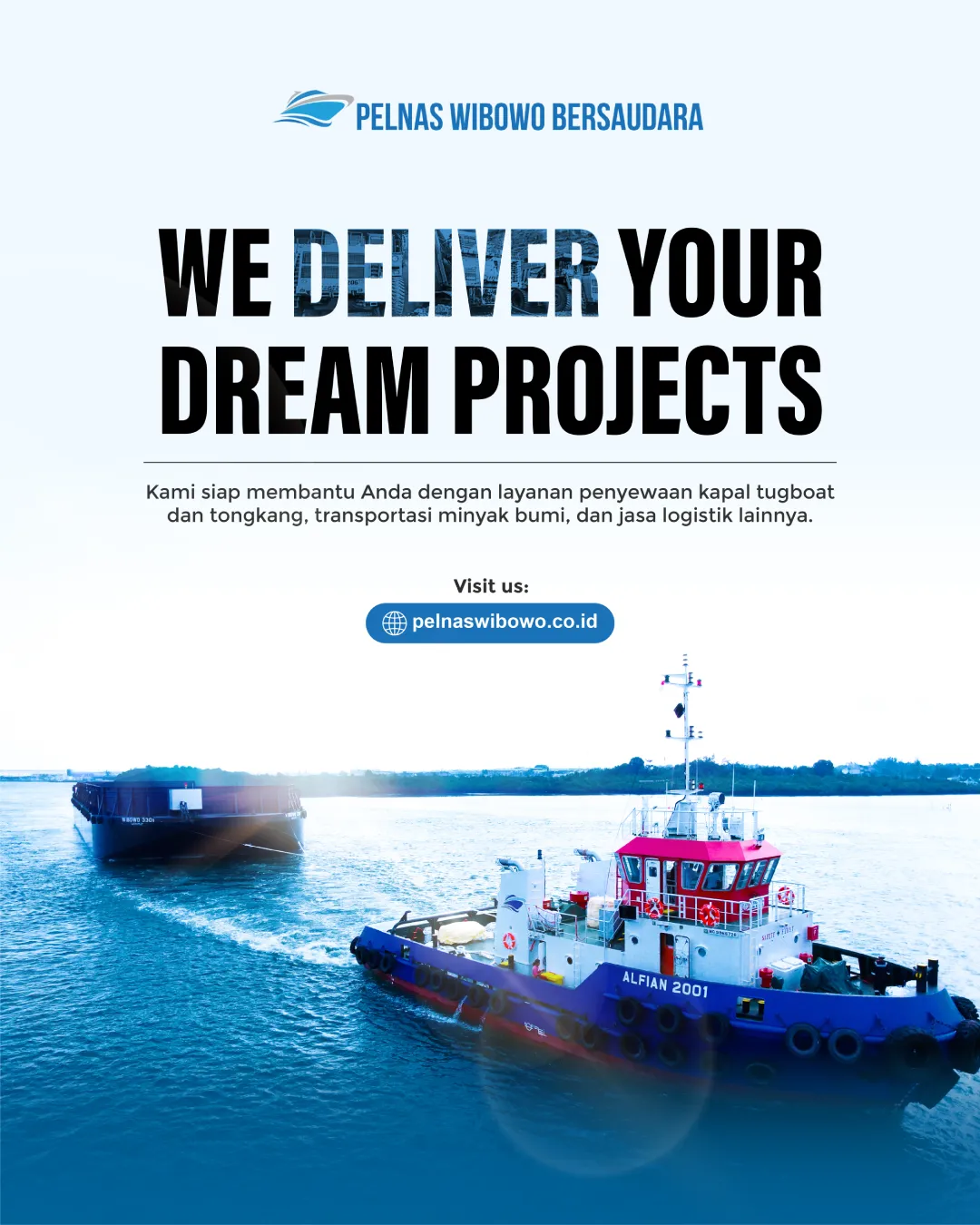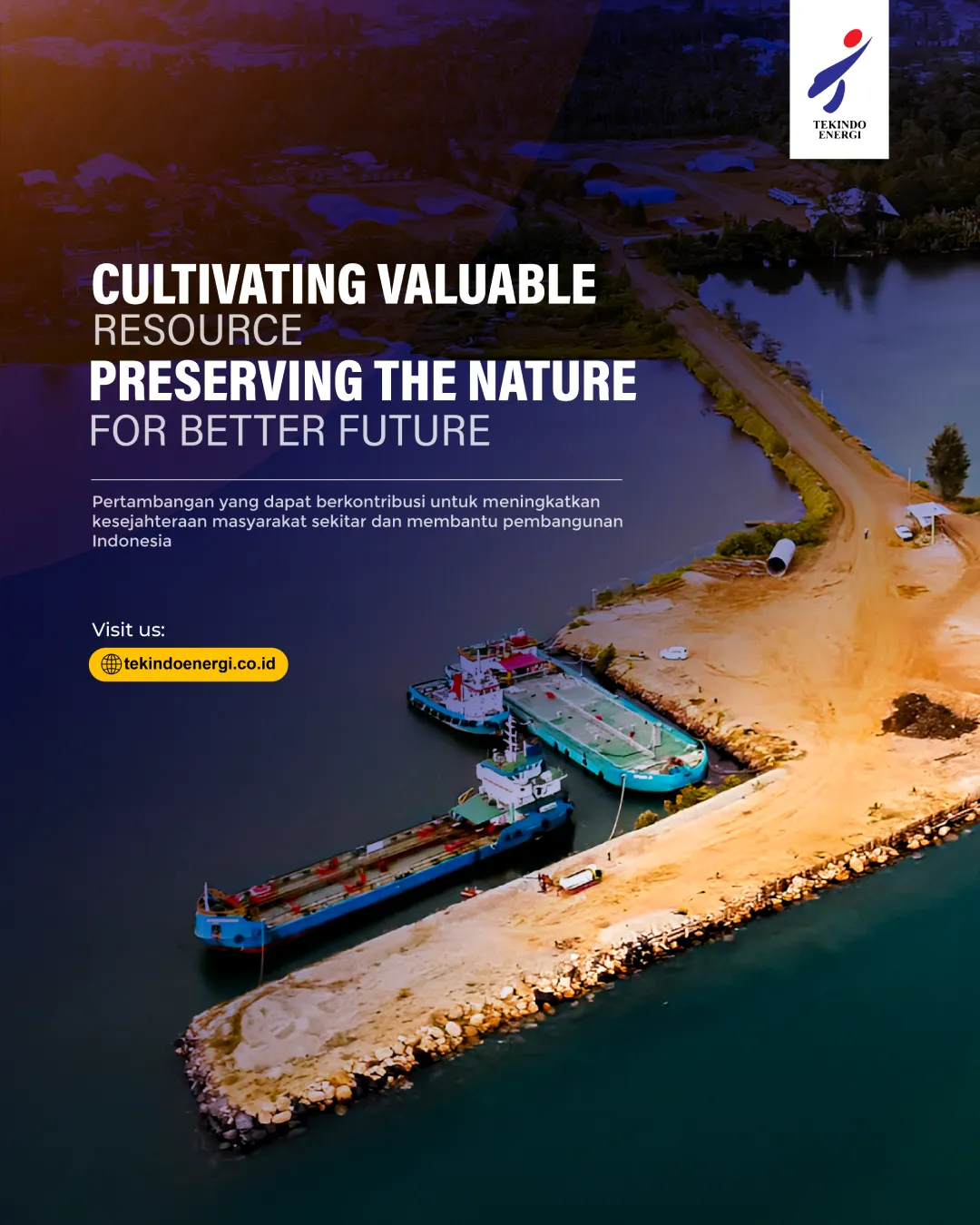BANDUNG, SUAR MAHASISWA AWARDS — “Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.” Itu bunyi SDGs nomor 4, seolah-olah semua anak di Indonesia bisa sekolah tanpa takut putus, bisa belajar teknologi terbaru, dan punya guru yang paham dunia digital. Tapi itu mungkin berlaku di Planet Kurikulon, sebuah dunia paralel tempat kurikulum selalu relevan, guru digaji dengan baik, dan murid di desa punya akses internet seperti di Jakarta Selatan.
Di belahan Bumi, tepatnya di Indonesia, realitasnya lebih bervariasi. Ada anak yang sekolah sambil bantu orang tua di ladang, ada yang rebutan sinyal, dan ada juga yang baru belajar tentang AI dari koran bekas bungkus gorengan.
Janji Manis dari Planet Beasisvaria
Beasiswa seharusnya jadi jalan pembuka menuju pendidikan yang setara. Tapi terkadang, prosesnya terasa seperti misi luar angkasa penuh persyaratan teknis, waktu yang sempit, dan orbit administrasi yang berliku.
Di Planet Beasisvaria, semua siswa berprestasi otomatis terdata dan langsung dapat bantuan, tanpa perlu mengisi 17 dokumen dan ikut seleksi rasa gacha. Sayangnya, di Bumi, beasiswa kadang jatuh ke tangan yang paling cepat submit bukan yang paling membutuhkan.
Kecerdasan Buatan, Ketidaksiapan Manusia
AI kini bisa menjawab soal ujian, menulis esai, bahkan bantu mahasiswa skripsi. Tapi sayangnya, sebagian institusi pendidikan kita masih ragu: “ChatGPT itu membantu atau menyesatkan?”
Di Galaksi EduTechia, AI digunakan sebagai alat belajar yang keren dan etis, guru dilatih untuk beradaptasi, dan murid diajari berpikir kritis. Di sini? Kita masih kirim tugas lewat WhatsApp dan bingung cara buka Google Classroom.
Ketika Desa dan Kota Ada di Dua Planet Berbeda
Satu kurikulum untuk semua. Idenya bagus. Tapi pelaksanaannya seperti menyamakan gravitasi antara Planet Perkotaan dan Planet DesaTertinggal. Di kota, anak SD diajari coding. Di desa, anak SMP masih rebutan buku paket. Bahkan ada sekolah yang masih pakai spidol bekas sumbangan dari acara TV. Tapi tenang, mereka juga harus lulus ujian nasional berbasis komputer. Ajaib, bukan?
Generasi Z dan TikTok Adalah Bentuk Komunikasi Alternatif dari Planet Zettanova
Sementara itu, harapan justru datang dari Generasi Z. Mereka tidak tinggal diam. Lewat TikTok, Instagram, dan podcast, banyak yang mulai menyuarakan isu pendidikan, berbagi informasi beasiswa, dan bahkan mengajar lewat konten.
Di Planet Zettanova, komunikasi digital adalah bentuk revolusi pendidikan tanpa birokrasi, tanpa batasan kelas sosial. Mungkin kita bisa belajar dari sana. kalau sinyal kita kuat.
Solusi? Kita Tak Butuh Roket, Cukup Kesadaran
Berikut beberapa langkah kecil namun signifikan untuk membuat pendidikan kita sedikit lebih membumi:
- Beasiswa harus berbasis data dan transparansi, bukan hanya kecepatan jari.
- Guru perlu pelatihan digital yang nyata, bukan sekadar webinar formalitas.
- Sekolah di desa perlu dukungan yang kontekstual, bukan copy-paste dari kota.
- Media sosial harus dianggap aset edukatif, bukan sekadar ancaman moral.
Turun Kembali ke Belahan Bumi Ini
Pendidikan berkualitas itu bukan mitos tapi juga belum jadi realitas. Kalau kita terus memajang SDGs di presentasi tapi lupa menanyakan bagaimana murid-murid di pelosok bertahan, mungkin kita memang masih tinggal di Planet Retorika, bukan Planet Solusi.
Tapi harapan belum punah. Selama masih ada yang peduli, bertanya, dan menulis (seperti kamu yang sedang membaca ini), maka masih ada kemungkinan kita semua pulang ke Bumi ke tempat di mana pendidikan benar-benar bisa mengubah nasib, bukan sekadar jadi materi seminar.
Penulis:
Billy Prayoga