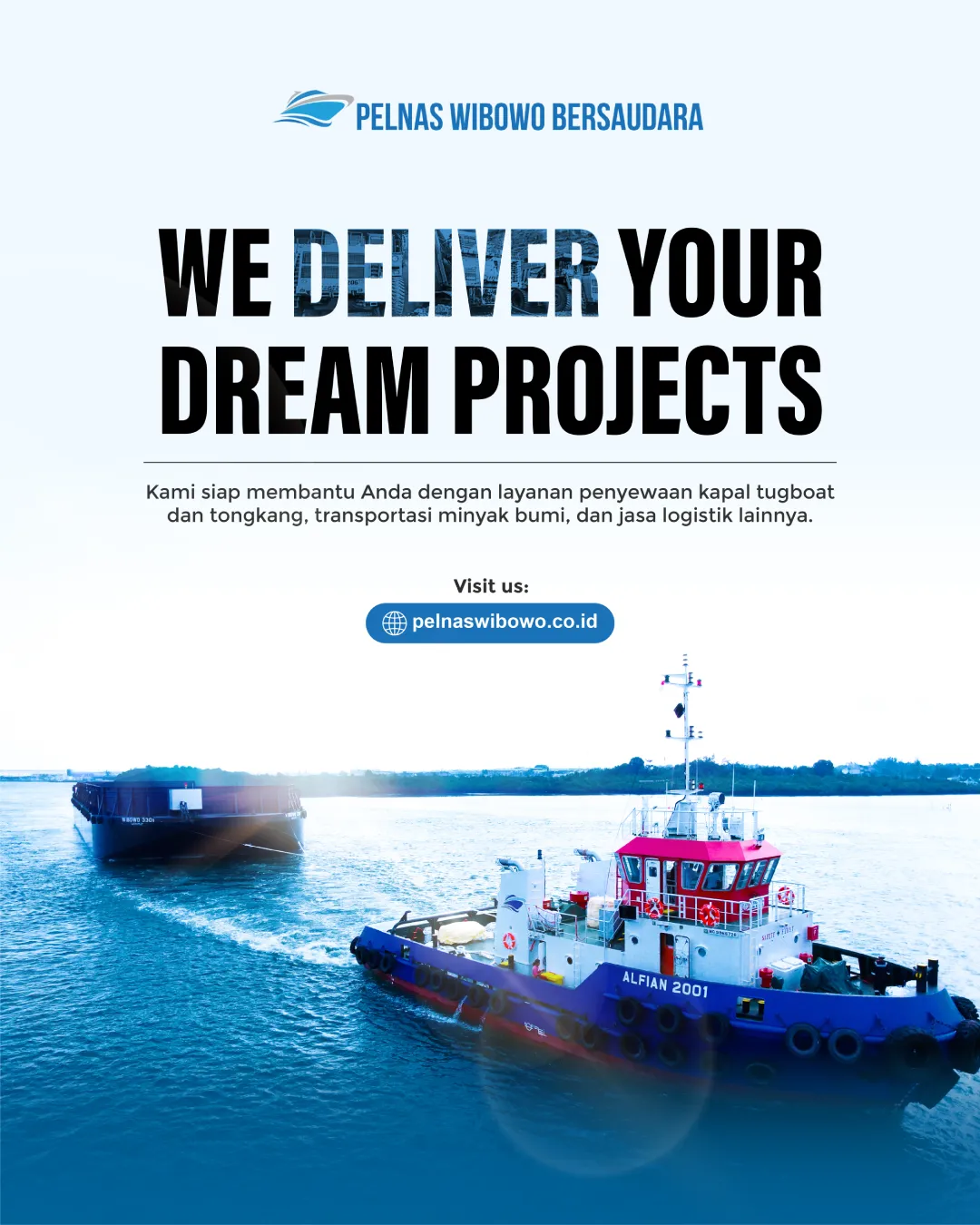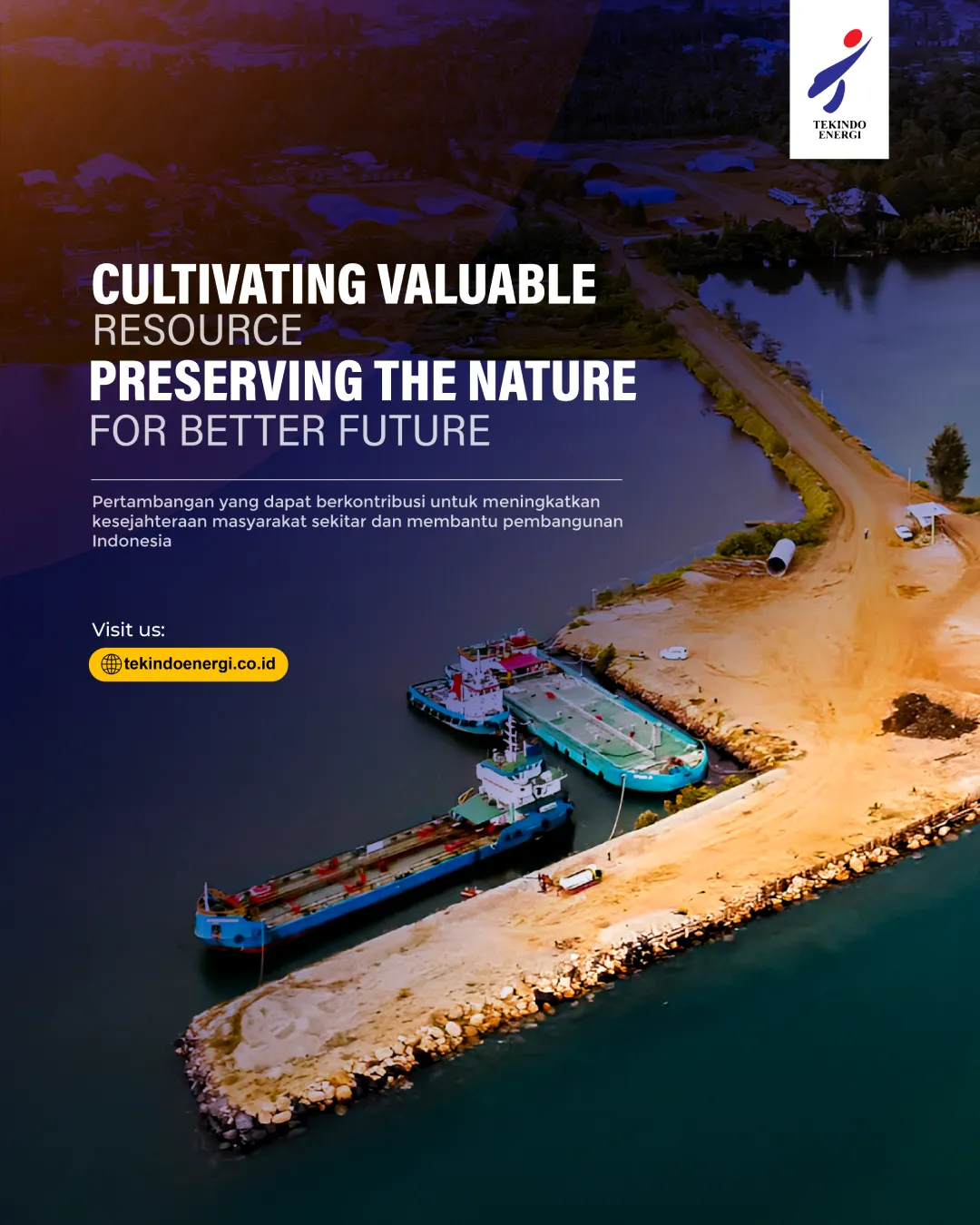SUAR MAHASISWA AWARDS — Beberapa tahun terakhir, publik—khususnya kalangan muda—dibuat tergila-gila oleh sosok kecil berbulu bernama Labubu, salah satu karakter dari lini boneka Pop Mart asal Tiongkok. Boneka ini bukan sekadar mainan biasa. Ia telah menjelma menjadi simbol status, pemicu ledakan impulsif belanja, dan cerminan budaya konsumerisme yang kian tak terkendali.
Dari Mainan Anak ke Budaya Kolektor Dewasa
Dulu, mainan identik dengan anak-anak. Kini, justru orang dewasa yang menjadi pasar utama. Pop Mart—merek yang didirikan Wang Ning pada 2010—membawa perubahan besar dalam industri ini dengan mengusung konsep blind box atau “kotak misterius.” Konsumen tidak tahu boneka mana yang mereka dapatkan sampai kotaknya dibuka. Konsep ini memicu rasa penasaran, adrenalin, dan akhirnya dorongan untuk membeli lagi dan lagi—semuanya demi mendapatkan varian langka.
Labubu: Boneka Viral yang Membakar Dompet
Karakter Labubu, hasil karya seniman Kasing Lung, menjadi salah satu ikon Pop Mart yang paling diburu. Viralitas Labubu memuncak ketika Lisa BLACKPINK memamerkannya di media sosial pada April 2024. Sejak itu, Labubu bukan hanya populer—ia menjadi kegilaan global.
Antrean di toko Pop Mart pun memanjang. Di Jakarta, Vietnam, hingga Los Angeles, orang rela menginap di depan toko demi satu kotak. Di e-commerce Indonesia, Labubu edisi tertentu pernah dijual hingga Rp66 juta. Ironisnya, banyak pembeli bahkan tak benar-benar menyukai bonekanya—mereka hanya takut ketinggalan tren, atau yang kini lebih dikenal sebagai efek FOMO (Fear of Missing Out).
Strategi Pop Mart: Seni atau Eksploitasi Psikologis?
Kesuksesan Pop Mart memang tidak lepas dari strategi marketing yang cerdik: kolaborasi eksklusif dengan seniman, edisi terbatas, dan sistem blind box. Mereka memahami satu hal: manusia suka kejutan, menyukai hal langka, dan seringkali membeli bukan karena butuh—tapi karena takut kehilangan kesempatan.
Namun, di balik kreativitas itu, muncul pertanyaan: apakah strategi ini mendorong kebiasaan konsumsi yang sehat? Banyak kolektor mengakui membeli secara impulsif dan merasa kecewa setelahnya. Tapi karena “tidak puas,” mereka membeli lagi. Ini menciptakan siklus tanpa akhir: repeat purchase yang dikendalikan bukan oleh kebutuhan, tapi oleh ilusi eksklusivitas.
Ketika Mainan Menjadi Status Sosial
Tak dapat disangkal, Labubu telah berubah dari boneka menjadi simbol status. Bryanboy, fashion influencer ternama, bahkan menyematkannya pada tas Hermès Birkin yang bernilai ratusan juta. “Kontras antara boneka murah dan tas mahal itulah yang membuatnya menarik,” ungkapnya.
Namun, apakah makna di balik koleksi sudah bergeser? Kini, semakin banyak kamu punya Labubu, semakin tinggi reputasimu dalam komunitas kolektor. Seolah-olah nilai diri ditentukan oleh seberapa banyak “makhluk lucu bermata tajam” itu ada di lemarimu.
Refleksi: Hobi, Gaya Hidup, atau Obsesi?
Tidak salah jika seseorang ingin mengoleksi sesuatu yang mereka sukai. Namun ketika kegemaran berubah menjadi kebiasaan belanja impulsif, tekanan sosial, hingga pengeluaran tak terkendali, saatnya kita bertanya: apakah kita mengoleksi Labubu, atau justru Labubu yang mulai ‘memiliki’ kita?
Budaya Pop Mart memberi pelajaran tentang bagaimana visual, psikologi, dan pemasaran dapat membentuk perilaku manusia. Tapi ia juga menjadi cermin tentang bagaimana kita perlu menyeimbangkan antara keinginan dan kendali diri.
Penulis:
Azzahra Dwi Savana Dinata