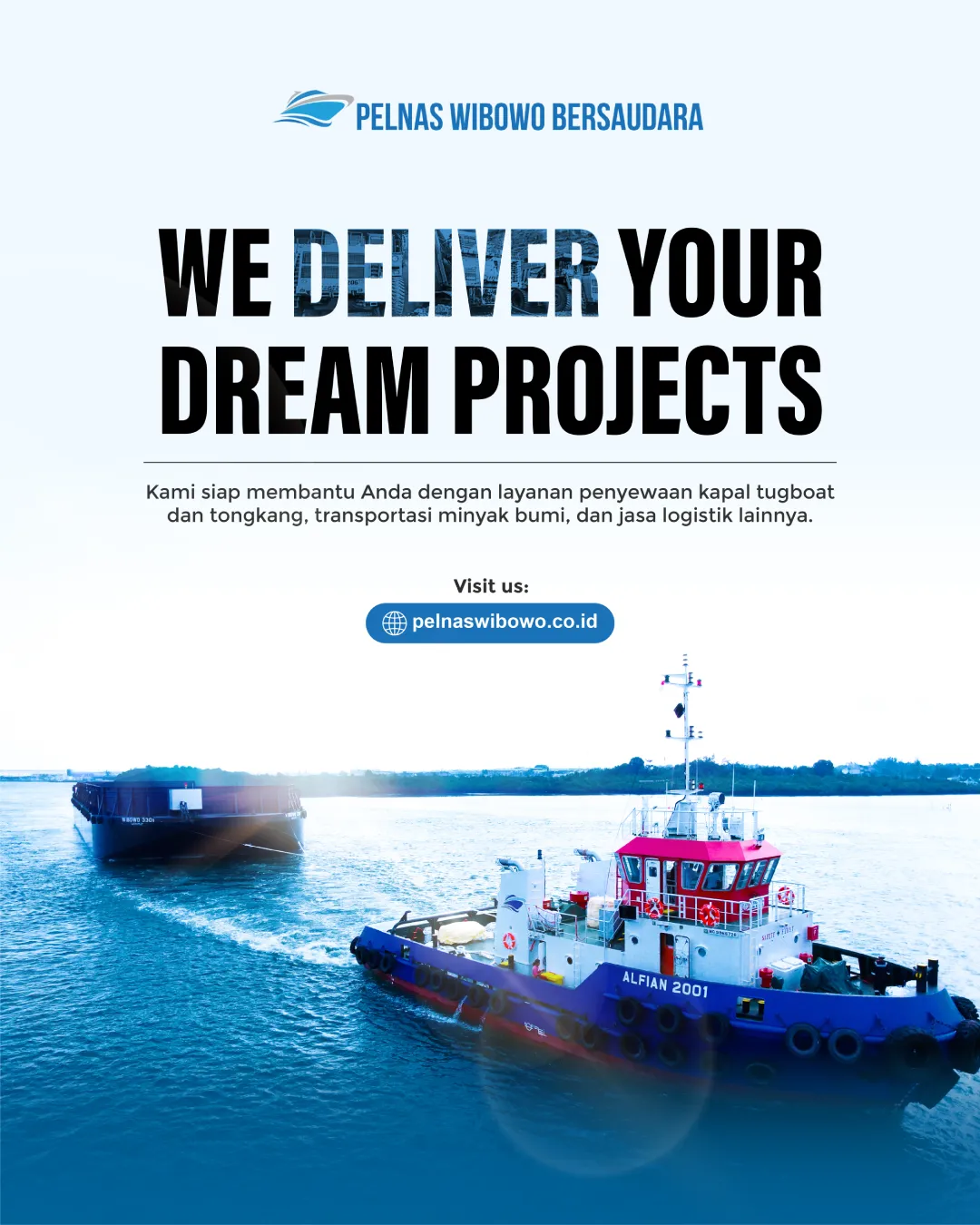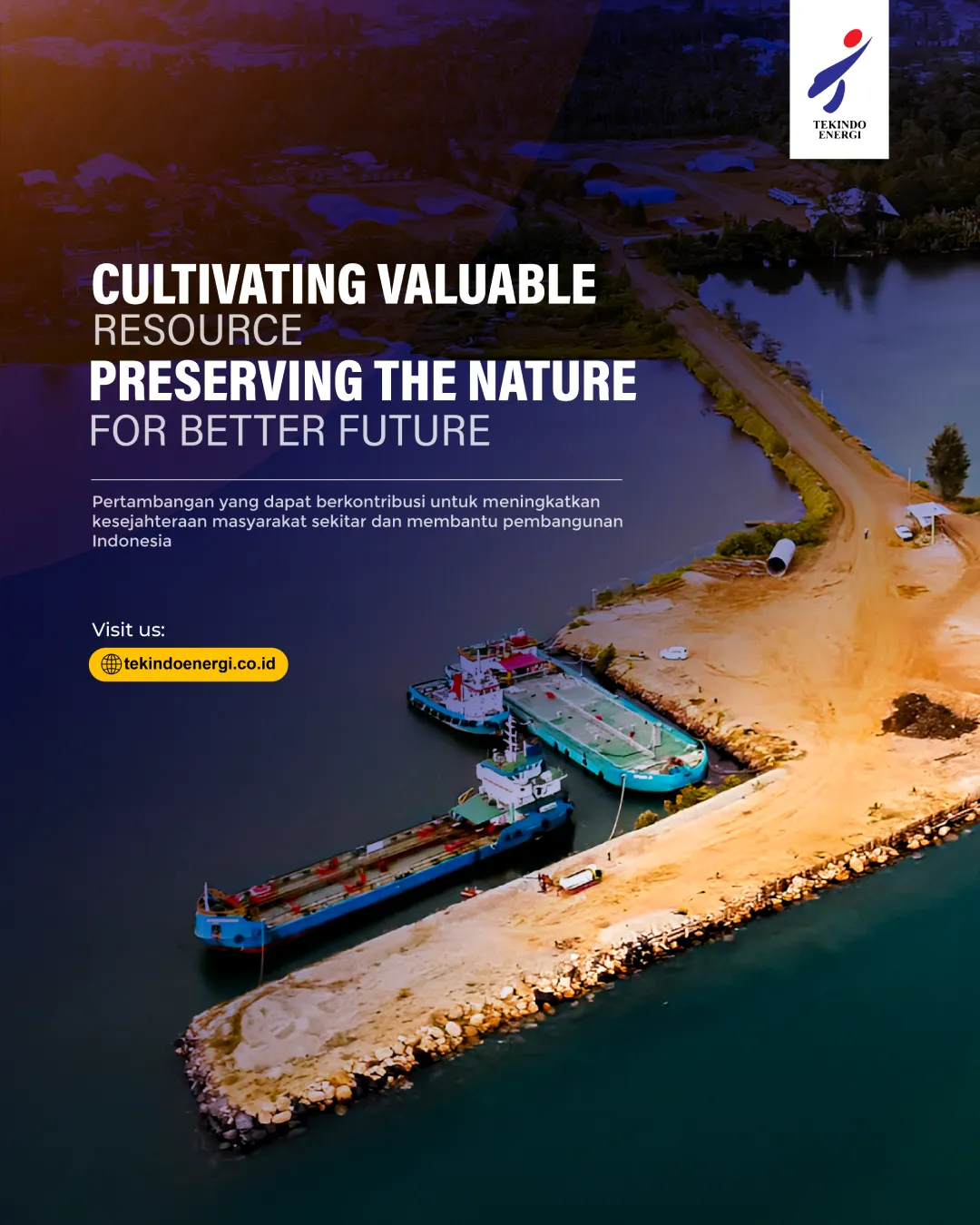BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Belakangan ini, istilah hustle culture semakin lekat dalam kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda.
Budaya kerja keras yang dulunya dianggap sebagai hal positif, kini berubah menjadi beban sosial yang tak terlihat. Bekerja tanpa henti, padat aktivitas, dan selalu produktif seakan menjadi tolok ukur keberhasilan.
Di era digital, media sosial memainkan peran penting dalam membentuk persepsi ini. Unggahan soal kerja lembur, rapat beruntun, atau proyek tanpa jeda kerap dilihat sebagai simbol sukses.
Di sisi lain, waktu istirahat dipandang sebagai kelemahan, dan ritme lambat dianggap tertinggal. Dalam perspektif sosiologi komunikasi, budaya ini menunjukkan bagaimana bahasa, simbol, dan media berperan dalam menciptakan tekanan sosial.
Ucapan seperti “jangan buang waktu”, “upgrade diri terus”, atau “kerja keras dulu, nikmati nanti” membentuk norma yang menekan banyak individu, hingga melupakan kebutuhan dasar mereka beristirahat, merasa cukup, dan hidup seimbang.
Baca Juga:
Fenomena Fatherless: Dampak Ketidakhadiran Ayah Terhadap Kehidupan Anak
Mengenal Kekerasan Seksual Digital: Dari Edukasi hingga Healing di “Safe and Grow”
Tak hanya itu, hustle culture juga menyimpan bias gender yang tidak selalu disadari. Perempuan kerap menghadapi tuntutan ganda sukses di luar rumah, namun tetap memegang peran domestik.
Di sisi lain, laki-laki sering merasa dituntut untuk terus aktif dan berpengaruh demi memenuhi ekspektasi maskulinitas. Hal ini memperlihatkan bahwa komunikasi sosial juga turut membentuk dan memperkuat harapan berbasis gender.
Survei Jakpat tahun 2024 menyebutkan bahwa 71% anak muda merasa belum sukses jika tidak terlihat sibuk setiap hari. Banyak di antaranya merasa cemas, kehilangan arah, bahkan menjauh dari interaksi sosial karena tekanan ini.
Pola komunikasi pun bergeser, dari ruang berbagi menjadi ajang menunjukkan diri. Melalui rilis ini, penulis ingin mengajak masyarakat untuk kembali mempertanyakan apakah sibuk selalu berarti sukses?
Sudah waktunya kita membangun budaya komunikasi yang lebih sehat yang memberi ruang jeda, menghargai proses, dan tidak menjadikan kesibukan sebagai satu-satunya ukuran nilai diri.
(Mega Rahma Adelia/ Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Sosial, Bhakti Kencana University)