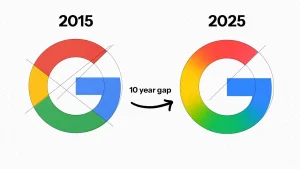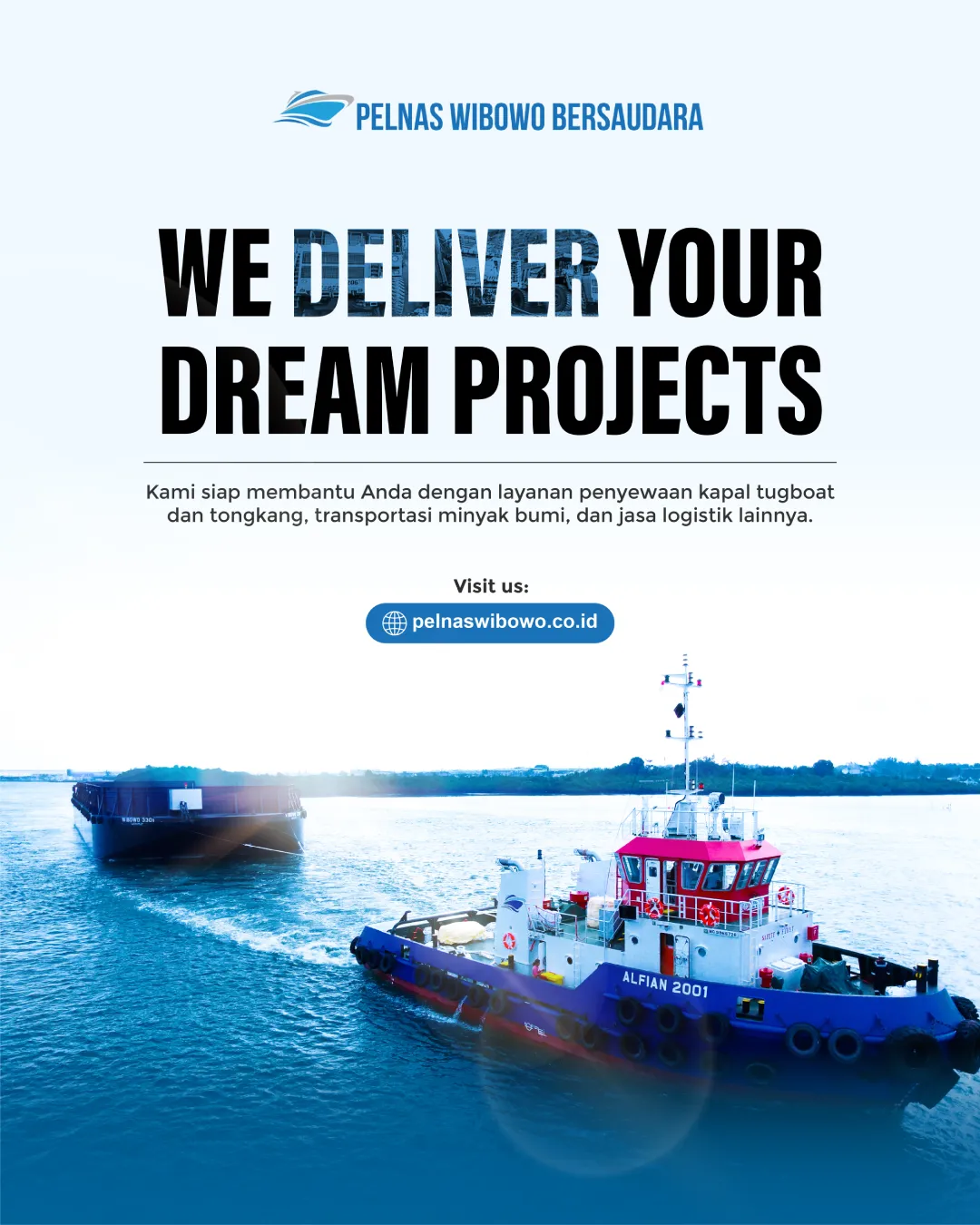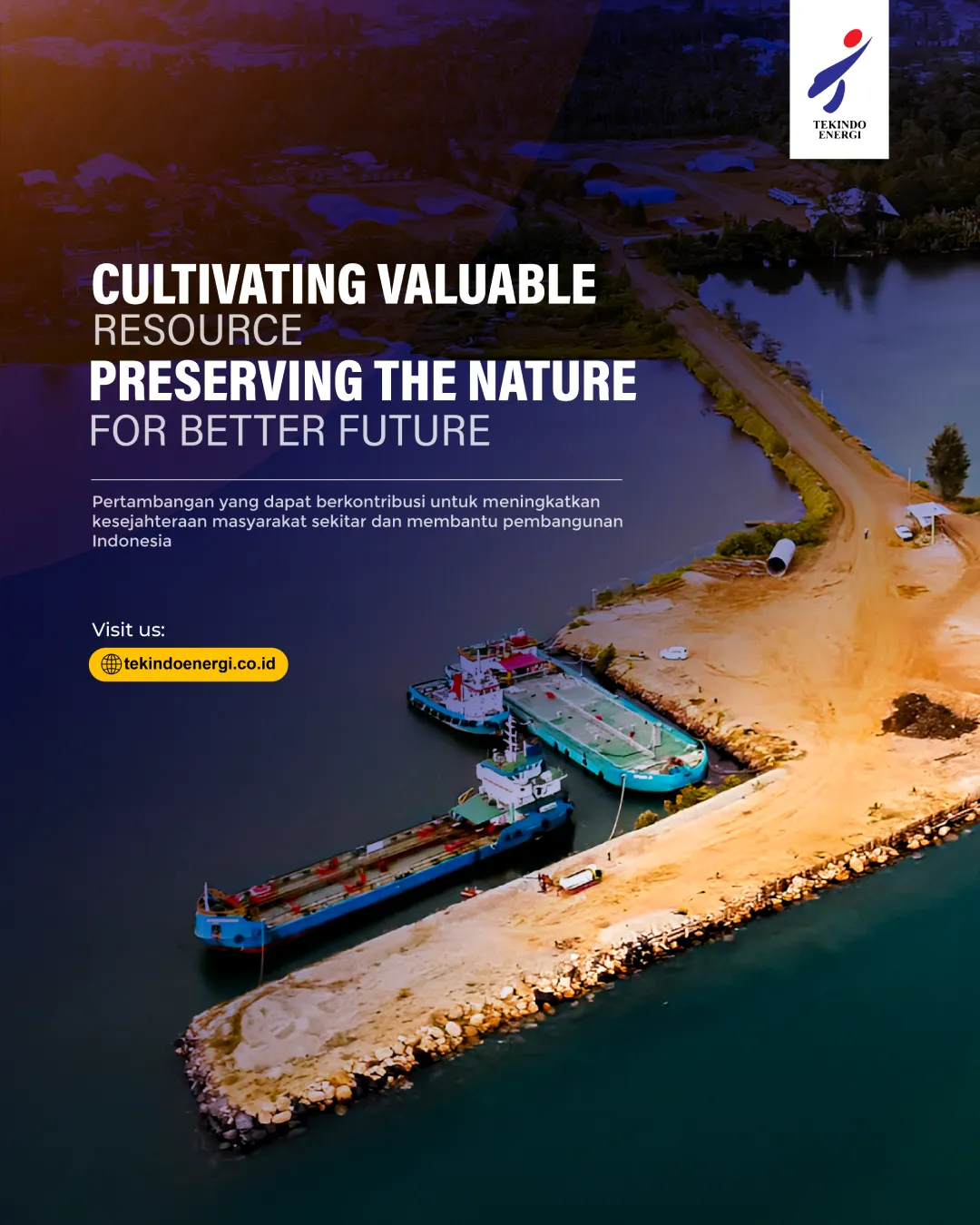BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Bayangkan sebuah algoritma mengetahui kapan Anda akan mati dan bukan berdasarkan firasat atau ramalan bintang, melainkan data riil rekam medis, status pekerjaan, hingga intensitas liburan Anda.
Kedengarannya seperti fiksi distopia, namun kini tengah menjadi kenyataan lewat teknologi buatan tim peneliti Denmark yang dinamai Death Clock.
Dipublikasikan dalam Nature Computational Science, sistem ini dikembangkan dari data 6 juta warga Denmark selama 15 tahun.
Bukan sekadar alat bantu medis, Death Clock membawa kita pada pertanyaan besar: apakah hidup tetap bermakna jika kematian bisa diprediksi dengan akurasi 78%?
Berbeda dari dokter yang mengandalkan pengalaman dan intuisi, Death Clock bekerja layaknya ChatGPT versi kehidupan manusia.
Algoritma ini tak hanya membaca gejala medis, tetapi juga membaca “alur cerita hidup” dari catatan rawat inap hingga status perkawinan dan fluktuasi penghasilan.
“Hidup kita, seperti sebuah simfoni. AI hanya membaca harmoni dan disonansinya,” ujar peneliti utama dari Technical University of Denmark, Prof. Sune Lehmann.
Dengan akurasi jauh lebih tinggi dibandingkan dokter (75% vs 58% untuk prediksi kematian dini), potensi manfaat Death Clock tak terbantahkan, terutama dalam mengatur prioritas layanan medis atau perencanaan hidup sehat. Namun di sisi lain, teknologi ini membuka kotak Pandora etika.
“Bayangkan perusahaan asuransi atau HRD menggunakan skor hidup Anda untuk menolak lamaran kerja atau menaikkan premi,” ujar ahli etika AI dari ETH Zurich, Effy Vayena.
Apakah manusia masih punya kendali, jika algoritma menganggap hidup mereka ‘tak layak investasi’?
Tidak berhenti di ruang riset, teknologi seperti ini mulai masuk ke ruang publik. Aplikasi seperti Endgame dan Death Clock versi filter Instagram kini ramai digunakan, seakan kematian bisa dipoles jadi hiburan digital.
Menariknya, survei Pew Research Center menunjukkan perpecahan: 62% tak ingin tahu kapan akan mati, namun 28% mayoritas generasi milenial justru penasaran.
Budaya quantified self tampaknya telah membuat kematian terasa seperti sekadar angka di dashboard kesehatan.
Baca Juga:
Tong Tong, Bayi Kecerdasan Buatan Pertama di Dunia
Dampak emosionalnya bukan main-main. Dalam studi Journal of Medical Ethics, diketahui bahwa sebagian besar pengguna merasa cemas, bahkan mengalami gejala AI Mortality Stress Syndrome (AMSS), sejenis gangguan baru yang banyak ditemukan di klinik mental Skandinavia.
Sebagian orang memang menjadi lebih termotivasi, tapi tak sedikit pula yang menyerah karena merasa “waktu mereka tinggal menghitung hari”.
Dr. Elena Martinez dari Universitas Barcelona menyebutnya “Pedang Damocles digital”, beban yang selalu menggantung di atas kepala pengguna.
Dengan proyeksi nilai pasar mencapai $1,2 miliar pada 2026, teknologi prediksi kematian bukan tren sesaat.
Tapi sebelum dunia berlomba membuat hidup makin bisa diprediksi, kita perlu bertanya ulang, apa arti menjadi manusia di tengah algoritma yang bisa mengukur eksistensi kita seperti jam pasir digital?
Death Clock adalah cermin masa depan yang bisa sangat bermanfaat, namun juga bisa menggerus esensi harapan, ketidakpastian, dan pilihan bebas yang menjadikan manusia berbeda dari mesin.
(Budis)